Ānanda
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari Ānanda di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan. Jika Anda menguasai bahasa aslinya, harap pertimbangkan untuk menelusuri referensinya dan menyempurnakan terjemahan ini. Anda juga dapat ikut bergotong royong pada ProyekWiki Perbaikan Terjemahan. (Pesan ini dapat dihapus jika terjemahan dirasa sudah cukup tepat. Lihat pula: panduan penerjemahan artikel) |
Ānanda (Pali dan Sanskerta: आनन्द; abad ke-5–ke-4 SM) adalah pelayan utama sekaligus salah satu dari sepuluh murid agung Sang Buddha. Di antara para murid Sang Buddha, Ānanda dikenal karena memiliki ingatan yang luar biasa. Sebagian besar teks Buddhis awal yang terkandung dalam Sutta-Piṭaka (Pāli: सुत्त पिटक; bahasa Sanskerta: सूत्र-पिटक, Sūtra-Piṭaka) didasarkan pada ingatan Ānanda akan ajaran Sang Buddha, yang kemudian dituturkannya secara lisan dalam Sidang Buddhis Pertama. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai Penjaga Perbendaharaan Dhamma (bahasa Pali: धम्मभण्डागारिक, translit. dhamma bhaṇḍāgārika), dengan dhamma mengacu pada ajaran Sang Buddha.
Bhante, Thera (Yang Mulia, Tetua) Ānanda | |
|---|---|
 Kepala Ānanda, pernah menjadi bagian dari patung batu kapur dari Gua Xiangtangshan utara. Dinasti Qi Utara, 550–577 M. | |
| Gelar | Patriark Dharma (tradisi Sanskerta) |
| Nama lain | Videhamuni; Dhamma-bhaṇḍāgārika ('Bendahara Dhamma') |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Abad ke-5–ke-4 SM |
| Meninggal | 20 tahun setelah kematian Sang Buddha Di Sungai Rohīni dekat Vesālī, atau Sungai Gangga |
| Agama | Buddhisme |
| Orang tua | Raja Śuklodana atau Raja Amitodana; Ratu Mrgī (tradisi Sanskerta) |
| Dikenal sebagai | Menjadi pelayan Sang Buddha (aggupaṭṭhāyaka);[1] kekuatan memori; belas kasihan kepada wanita |
| Kedudukan senior | |
| Guru | Sang Buddha; Puṇṇa Mantānīputta |
| Konsekrasi | Mahākassapa |
| Pendahulu | Mahākassapa |
| Penerus | Majjhantika atau Sāṇavāsī |
Siswa
| |
| Inisiasi | Tanggal 20 (Mūlasarvāstivāda) atau tahun ke-2 (tradisi lain) dari pelayanan Sang Buddha Nigrodhārāma atau Anupiya, Malla oleh Daśabāla Kāśyapa atau Belaṭṭhasīsa |
| Bagian dari seri tentang |
| Buddhisme |
|---|
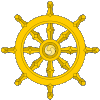
 |
Dalam teks Buddhis awal, Ānanda disebut sebagai sepupu Sang Buddha dan murid dari Puṇṇa Mantānīputta. Setelah dua puluh tahun menjadi bhikkhu, Ānanda dipilih oleh Sang Buddha untuk menjadi pelayan pribadinya. Dengan penuh pengabdian, Ānanda melaksanakan tugasnya sebagai perantara antara Sang Buddha dengan umat, termasuk dalam saṅgha. Ānanda melayani Sang Buddha hingga akhir hidupnya, bertindak sebagai sekretaris dan juru bicara.
Para sarjana meragukan kebenaran historis berbagai riwayat kehidupan Ānanda, terutama terkait perannya dalam Sidang Pertama. Berdasarkan catatan tradisional dari riwayat awal, komentar-komentar Tipiṭaka (aṭṭhakathā), dan kronik non-sutra, dikisahkan bahwa Ānanda memiliki peran penting dalam mendirikan tatanan bhikkhunī (bahasa Sanskerta: भिक्षुणी), dengan meminta kepada Sang Buddha agar mengizinkan ibu angkatnya, Mahāpajāpati Gotamī (bahasa Sanskerta: महाप्रजापती गौतमी, Mahāprajāpatī Gautamī) untuk ditahbiskan. Ānanda juga menemani Sang Buddha di tahun-tahun akhir hidupnya, sehingga menjadi saksi banyak ajaran dan prinsip yang disampaikan Sang Buddha sebelum kematian-Nya, termasuk ajaran bahwa kaum Buddhis harus mengambil ajaran dan kedisiplinan sebagai perlindungan mereka, dan Sang Buddha tidak akan menunjuk pemimpin baru sebagai penggantinya.
Tak lama setelah kematian Sang Buddha, Sidang Buddhis Pertama diadakan. Menurut catatan tradisional, Ānanda mencapai pencerahan tepat sebelum sidang dimulai, yang merupakan syarat untuk mengikuti sidang tersebut. Selama sidang berlangsung, Ānanda menjadi sumber ingatan hidup Sang Buddha, melafalkan banyak khotbah Sang Buddha serta memeriksa keakuratannya. Namun, dalam sidang yang sama, ia mendapat kritik dari Mahākassapa (bahasa Sanskerta: महाकाश्यप, Mahākāśyapa) dan para saṅgha karena membiarkan kaum wanita ditahbiskan serta dianggap lalai menghormati Sang Buddha pada beberapa peristiwa penting. Pasca Sidang Pertama, Ānanda mengajar hingga akhir hayatnya dan mewariskan ajaran spiritualnya kepada murid-muridnya, antara lain Sāṇavāsī (bahasa Sanskerta: शाणकवासी, Śāṇakavāsī) dan Majjhantika (bahasa Sanskerta: मध्यान्तिक, Madhyāntika), yang kemudian berperan penting dalam Sidang Kedua dan Ketiga. Ānanda meninggal 20 tahun setelah kematian Sang Buddha, dan stūpa-stūpa (monumen) dibangun di sungai tempat ia meninggal.
Ānanda adalah salah satu tokoh yang paling dicintai dalam Buddhisme. Dia dikenal karena ingatannya, pengetahuannya, dan welas asihnya, sering dipuji oleh Sang Buddha atas keutamaannya. Dalam tradisi tekstual Sanskerta, Ānanda dianggap sebagai patriark Dhamma yang berdiri dalam garis keturunan spiritual, menerima ajaran dari Mahākassapa dan meneruskannya kepada murid-muridnya. Ānanda dihormati oleh para bhikkhunī sejak awal abad pertengahan atas jasanya dalam mendirikan ordo biarawati dan mengizinkan wanita ditahbiskan. Konon, kisah hidupnya menginspirasi komposer Richard Wagner dan penyair India Rabindranath Tagore dalam karya-karya mereka.
Nama
suntingKata "ānanda" (आनन्द) dalam bahasa Pāli dan Sanskerta berarti 'kebahagiaan, kegembiraan'.[2][3] Dalam Atthakatha (Komentar Pāli) disebutkan bahwa ketika Ānanda lahir, kerabatnya menyambutnya dengan gembira. Namun, teks-teks dari tradisi Mūlasarvāstivāda menyatakan bahwa karena Ānanda lahir pada hari pencerahan Sang Buddha, terjadi kegembiraan besar di kota tersebut, sesuai dengan namanya.[1]
Catatan
suntingKehidupan sebelumnya
suntingMenurut riwayat tradisional, dalam kehidupan sebelumnya, Ānanda bercita-cita menjadi pelayan Buddha. Ia memiliki keinginan ini saat hidup pada masa Buddha sebelumnya yang bernama Padumuttara, di tahun kalpa (bahasa Pali: kappa, bahasa Sanskerta: kalpa) sebelum era sekarang. Ānanda bertemu dengan pelayan Buddha Padumuttara dan bercita-cita menjadi seperti dia dalam kehidupan mendatang. Setelah melakukan banyak perbuatan baik, ia mengumumkan tekadnya kepada Buddha Padumuttara, yang kemudian menegaskan bahwa keinginannya akan terkabul di kehidupan mendatang. Setelah melalui siklus samsara dalam banyak kehidupan, ia terlahir sebagai Ānanda pada masa Buddha Gautama.[4]
Masa muda
suntingĀnanda lahir pada periode waktu yang sama dengan Sang Buddha (sebelumnya Pangeran Siddhattha), yang oleh para sarjana ditempatkan pada abad ke-5–4 SM.[5] Tradisi mengatakan bahwa Ānanda adalah sepupu pertama Sang Buddha,[6] ayahnya adalah saudara Suddhodana (bahasa Sanskerta: Śuddhodana), ayah Buddha.[7] Dalam tradisi tekstual Pāli dan Mūlasarvāstivāda, ayahnya adalah Amitodana (bahasa Sanskerta: Amṛtodana), tetapi Mahāvastu menyatakan bahwa ayahnya adalah Śuklodana—keduanya adalah saudara Suddhodana.[1] Mahāvastu juga menyebutkan bahwa nama ibu nanda adalah Mṛgī (Sanskerta; harfiah 'rusa kecil'; Pāli tidak diketahui).[8][1] Tradisi Pāli mengatakan bahwa Ānanda lahir pada hari yang sama dengan Pangeran Siddhatta (bahasa Sanskerta: Siddhārtha),[8] tetapi teks-teks dari Mūlasarvāstivāda dan tradisi Mahāyāna berikutnya menyatakan Ānanda lahir pada saat yang sama Sang Buddha mencapai pencerahan (ketika Pangeran Siddhattha berusia 35 tahun), dan karena itu jauh lebih muda dari Sang Buddha.[1] Tradisi yang terakhir ini dikuatkan oleh beberapa contoh dalam Teks Buddhis Awal, di mana Ānanda tampak lebih muda dari Sang Buddha, seperti perikop di mana Sang Buddha menjelaskan kepada nanda bagaimana usia tua mempengaruhi dirinya dalam tubuh dan pikiran. Hal ini juga dikuatkan oleh sebuah syair dalam teks Pāli yang berjudul Theragāthā, di mana Ānanda menyatakan bahwa dia adalah seorang "pelajar" selama dua puluh lima tahun, setelah itu ia menghadiri Sang Buddha selama dua puluh lima tahun lagi.[1][9]
Mengikuti tradisi tekstual Pāli, Mahīśasaka dan Dharmaguptaka, Ānanda menjadi seorang bhikkhu pada tahun kedua pelayanan Sang Buddha, selama kunjungan Sang Buddha ke Kapilavatthu (bahasa Sanskerta: Kapilavastu). Dia ditahbiskan oleh Buddha sendiri, bersama dengan banyak pangeran lain dari klan Buddha (bahasa Pali: Sākiya, bahasa Sanskerta: Śākya),[8] di hutan mangga yang disebut Anupiya, bagian dari wilayah Malla.[1] Menurut sebuah teks dari tradisi Mahāsaṅghika, Raja Suddhodana ingin Sang Buddha memiliki lebih banyak pengikut dari kasta khattiya (bahasa Sanskerta: kṣatriyaḥ), dan kurang dari kasta brahmana (pendeta). Karena itu ia memerintahkan agar setiap khattiya yang memiliki saudara laki-laki mengikuti Sang Buddha sebagai seorang bhikkhu, atau saudaranya melakukannya. Ānanda menggunakan kesempatan ini, dan meminta saudaranya Devadatta untuk tinggal di rumah, sehingga dia bisa pergi ke kebhikkhuan.[10] Garis waktu kemudian dari teks-teks Mūlasarvāstivāda dan Pāli Theragāthā, bagaimanapun, telah Ānanda menahbiskan jauh kemudian, sekitar dua puluh lima tahun sebelum kematian Sang Buddha—dengan kata lain, dua puluh tahun dalam pelayanan Sang Buddha.[1] Beberapa sumber Sanskerta menyuruhnya ditahbiskan bahkan kemudian.[11] Teks Mūlasarvāstivāda tentang disiplin monastik (Pāli dan bahasa Sanskerta: Vinaya) menceritakan bahwa para peramal meramalkan Ānanda akan menjadi pelayan Sang Buddha. Untuk mencegah Ānanda meninggalkan istana untuk ditahbiskan, ayahnya membawanya ke Vesālī (bahasa Sanskerta: Vaiśālī) selama kunjungan Sang Buddha ke Kapilavatthu, tetapi kemudian Sang Buddha bertemu dan mengajar Ānanda.[12] Pada catatan yang sama, Mahāvastu menceritakan, bagaimanapun, bahwa Mṛgī pada awalnya menentang Ānanda bergabung dengan kehidupan suci, karena saudaranya Devadatta telah ditahbiskan dan meninggalkan istana. Ānanda menanggapi perlawanan ibunya dengan pindah ke Videha (bahasa Sanskerta: Vaideha) dan tinggal di sana, bersumpah untuk diam. Ini membuatnya mendapatkan julukan Videhamuni (bahasa Sanskerta: Vaidehamuni), artinya 'orang bijak yang pendiam dari Videha'.[12] Ketika nanda ditahbiskan, ayahnya menyuruhnya ditahbiskan di Kapilavatthu di vihara Nigrodhārāma (bahasa Sanskerta: Niyagrodhārāma) dengan banyak upacara, pembimbing Ānanda (bahasa Pali: upajjhāya; bahasa Sanskerta: upādhyāya) menjadi Daśabāla Kāśyapa tertentu.[12]
Menurut tradisi Pāli, guru pertama Ānanda adalah Belaṭṭhasīsa dan Puṇṇa Mantānīputta. Ajaran Puṇṇa-lah yang menuntun nanda mencapai tingkat sotāpanna (bahasa Sanskerta: śrotāpanna), pencapaian yang mendahului pencerahan. Ānanda kemudian mengungkapkan hutangnya kepada Puṇṇa.[8][13] Tokoh penting lainnya dalam kehidupan Ānanda adalah Sāriputta (bahasa Sanskerta: Śāriputra), salah satu murid utama Buddha. Sāriputta sering mengajarkan nanda tentang poin-poin penting dari doktrin Buddhis;[14] mereka memiliki kebiasaan berbagi hal satu sama lain, dan hubungan mereka digambarkan sebagai persahabatan yang baik.[15] Dalam beberapa teks Mūlasarvāstivāda, seorang pelayan Ānanda juga disebutkan yang membantu memotivasi Ānanda ketika dia dilarang dari Sidang Buddhis Pertama. Dia adalah seorang "Vajjiputta" (bahasa Sanskerta: Vṛjjiputra), yaitu seseorang yang berasal dari konfederasi Vajji.[16] Menurut teks-teks selanjutnya, seorang bhikkhu yang tercerahkan juga disebut Vajjiputta (bahasa Sanskerta: Vajraputra) memiliki peran penting dalam kehidupan Ānanda. Dia mendengarkan ajaran Ānanda dan menyadari bahwa Ānanda belum tercerahkan. Vajjiputta mendorong Ānanda untuk sedikit berbicara dengan umat awam dan memperdalam latihan meditasinya dengan mundur ke dalam hutan, nasehat yang sangat mempengaruhi Ānanda.[17][18]
Menghadiri Sang Buddha
suntingDalam dua puluh tahun pertama pelayanan Sang Buddha, Sang Buddha memiliki beberapa pelayan pribadi.[8] Namun, setelah dua puluh tahun ini, ketika Sang Buddha berusia 55 tahun,[note 1] Sang Buddha mengumumkan bahwa Beliau membutuhkan seorang pelayan tetap.[7] Sang Buddha telah bertambah tua, dan pelayan-pelayannya sebelumnya tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik.[8] Awalnya, beberapa murid utama Sang Buddha menanggapi permintaannya, tetapi Sang Buddha tidak menerima mereka. Sementara itu Ānanda tetap diam. Ketika dia ditanya mengapa, dia berkata bahwa Sang Buddha akan lebih tahu siapa yang harus dipilih, dan Sang Buddha menanggapinya dengan memilih Ānanda.[note 2] Ānanda setuju untuk mengambil posisi tersebut, dengan syarat dia tidak menerima keuntungan materi apapun dari Sang Buddha.[7][8] Menerima manfaat seperti itu akan membuka dirinya terhadap kritik bahwa ia memilih posisi itu karena motif tersembunyi. Dia juga meminta agar Sang Buddha mengizinkannya untuk menerima undangan atas namanya, izinkan dia untuk bertanya tentang doktrinnya, dan ulangi ajaran apa pun yang telah diajarkan Sang Buddha saat Ānanda tidak ada.[7][8] Permintaan ini akan membantu orang mempercayai Ānanda dan menunjukkan bahwa Sang Buddha bersimpati kepada pelayannya.[8] Lebih jauh lagi, Ānanda menganggap ini keuntungan nyata menjadi seorang pelayan, itulah sebabnya dia memintanya.[2]
Sang Buddha menyetujui persyaratan Ānanda, dan Ānanda menjadi pelayan Sang Buddha, menemani Sang Buddha dalam sebagian besar perjalanannya. Ānanda mengurus kebutuhan praktis sehari-hari Sang Buddha, dengan melakukan hal-hal seperti membawa air dan membersihkan tempat tinggal Sang Buddha. Ia digambarkan sebagai orang yang taat dan setia, bahkan menjaga tempat tinggal pada malam hari.[8][2] Ānanda berperan sebagai lawan bicara dalam banyak dialog yang direkam. Dia merawat Buddha selama total 25 tahun,[6][8] tugas yang membutuhkan banyak pekerjaan.[19] Hubungannya dengan Buddha digambarkan sebagai hangat dan percaya:[20][21] ketika Sang Buddha jatuh sakit, Ānanda menderita penyakit simpatik;[8] ketika Sang Buddha tumbuh dewasa, Ānanda terus merawatnya dengan penuh pengabdian.[2]
Ānanda terkadang benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk gurunya. Pada suatu waktu, biksu pemberontak Devadatta mencoba membunuh Sang Buddha dengan melepaskan seekor gajah liar dan mabuk di hadapan Sang Buddha. Ānanda melangkah di depan Sang Buddha untuk melindunginya. Ketika Sang Buddha menyuruhnya untuk pindah, dia menolak, meskipun biasanya dia selalu mematuhi Sang Buddha.[8] Melalui pencapaian supranatural (bahasa Pali: iddhi; bahasa Sanskerta: ṛiddhi) Sang Buddha kemudian memindahkan Ānanda ke samping dan menaklukkan gajah itu, dengan menyentuhnya dan berbicara kepadanya dengan cinta kasih.[22]
Ānanda sering bertindak sebagai perantara dan sekretaris, menyampaikan pesan dari Sang Buddha, memberi tahu Buddha tentang berita, undangan, atau kebutuhan umat awam, dan menasihati umat awam yang ingin memberikan hadiah kepada saṅgha.[8][23] Pada suatu waktu, Mahāpajāpatī, ibu angkat Sang Buddha, meminta untuk mempersembahkan jubah untuk penggunaan pribadi bagi Sang Buddha. Dia berkata bahwa meskipun dia telah membesarkan Buddha di masa mudanya, dia tidak pernah memberikan apa pun secara pribadi kepada pangeran muda; dia sekarang ingin melakukannya. Sang Buddha awalnya bersikeras bahwa dia memberikan jubah itu kepada komunitas secara keseluruhan daripada dilampirkan pada pribadinya. Namun, Ānanda menengahi dan menengahi, menyarankan agar Sang Buddha lebih baik menerima jubah itu. Akhirnya Sang Buddha melakukannya, tetapi bukan tanpa menunjukkan kepada Ānanda bahwa perbuatan baik seperti memberi harus selalu dilakukan demi perbuatan itu sendiri, bukan demi orangnya.[24]
Teks-teks mengatakan bahwa Sang Buddha terkadang meminta Ānanda untuk menggantikannya sebagai guru,[25][26] dan sering dipuji oleh Sang Buddha atas ajarannya.[27] Ānanda sering diberi peran mengajar yang penting, seperti mengajar Ratu Mallikā secara teratur, Ratu Sāmāvatī, (bahasa Sanskerta: Śyāmāvatī) dan orang lain dari kelas penguasa.[28][29] Suatu ketika Ānanda mengajar sejumlah selir Raja Udena (bahasa Sanskerta: Udayana). Mereka sangat terkesan dengan ajaran Ānanda, sehingga mereka memberinya lima ratus jubah, yang diterima Ānanda. Setelah mendengar tentang hal ini, Raja Udena mengkritik Ānanda karena serakah; Ānanda menanggapi dengan menjelaskan bagaimana setiap jubah digunakan dengan hati-hati, digunakan kembali dan didaur ulang oleh komunitas monastik, mendorong raja untuk menawarkan lima ratus jubah lagi.[30] Ānanda juga berperan dalam kunjungan Sang Buddha ke Vesālī. Dalam cerita ini, Sang Buddha mengajarkan teks terkenal Ratana Sutta kepada Ānanda, yang kemudian dibacakan oleh Ānanda di Vesālī, membersihkan kota dari penyakit, kekeringan dan roh jahat dalam prosesnya.[31] Bagian lain yang terkenal di mana Sang Buddha mengajarkan Ānanda adalah bagian tentang persahabatan spiritual (bahasa Pali: kalyāṇamittata). Dalam bagian ini, Ānanda menyatakan bahwa persahabatan spiritual adalah setengah dari kehidupan suci; Sang Buddha mengoreksi Ānanda, menyatakan bahwa persahabatan seperti itu adalah seluruh kehidupan suci.[32][33] Singkatnya, Ānanda bekerja sebagai asisten, perantara dan juru bicara, membantu Sang Buddha dalam banyak hal, dan mempelajari ajarannya dalam prosesnya.[34]
Menahan godaan
suntingĀnanda berpenampilan menarik.[8] Sebuah catatan Pāli menceritakan bahwa seorang bhikkhunī (biarawati) menjadi terpikat dengan Ānanda, dan berpura-pura sakit agar Ānanda mengunjunginya. Ketika dia menyadari kesalahannya, dia mengakui kesalahannya kepada Ānanda.[35] Catatan lain menceritakan bahwa seorang wanita kasta rendah bernama Prakṛti (juga dikenal di Tiongkok sebagai 摩登伽女; Módēngqiénǚ) jatuh cinta pada Ānanda, dan membujuk ibunya Mātaṅgī untuk menggunakan mantra sihir hitam untuk memikatnya. Ini berhasil, dan Ānanda terpikat ke rumahnya, tetapi sadar dan meminta bantuan Sang Buddha. Sang Buddha kemudian mengajarkan Prakṛti untuk merenungkan kualitas menjijikkan dari tubuh manusia, dan akhirnya Prakṛti ditahbiskan sebagai bhikkhunī, melepaskan keterikatannya pada Ānanda.[36][37] Dalam versi Asia Timur dari cerita dalam Śūraṃgamasūtra, Sang Buddha mengirim Mañjuśr untuk membantu Ānanda, yang menggunakan pelafalan untuk melawan jimat sihir. Sang Buddha kemudian melanjutkan dengan mengajar Ānanda dan pendengar lainnya tentang sifat Buddha.[38]
Menetapkan perintah biarawati
suntingDalam peran sebagai mediator antara Buddha dan umat awam, Ānanda terkadang memberikan saran kepada Sang Buddha untuk perubahan dalam disiplin monastik.[39] Yang paling penting, teks-teks awal menghubungkan penyertaan wanita dalam saṅgha awal (ordo monastik) dengan Ānanda.[40] Lima belas tahun setelah pencerahan Sang Buddha, ibu angkatnya Mahāpajāpatī datang menemuinya untuk memintanya ditahbiskan sebagai bhikkhunī Buddhis pertama. Awalnya, Sang Buddha menolak ini. Lima tahun kemudian, Mahāpajāpatī datang untuk meminta Sang Buddha lagi, kali ini dengan pengikut wanita Sākiya lainnya, termasuk mantan istri Sang Buddha, Yasodharā (bahasa Sanskerta: Yaśodarā). Mereka telah berjalan 500 km, tampak kotor, lelah dan tertekan, dan Ānanda merasa kasihan pada mereka. Oleh karena itu Ānanda mengkonfirmasi dengan Sang Buddha apakah wanita bisa menjadi tercerahkan juga. Meskipun Sang Buddha mengakui hal ini, Beliau belum mengizinkan para wanita Sākiya untuk ditahbiskan. Ānanda kemudian berdiskusi dengan Sang Buddha bagaimana Mahāpajāpatī merawatnya selama masa kecilnya, setelah kematian ibu kandungnya.[41][42] Ānanda juga menyebutkan bahwa para Buddha sebelumnya juga telah menahbiskan bhikkhunī.[43] Pada akhirnya, Sang Buddha mengizinkan wanita Sākiya untuk ditahbiskan, menjadi awal dari ordo bhikkhunī.[41] Ānanda menyuruh Mahāpajāpatī ditahbiskan dengan menerima seperangkat aturan, yang ditetapkan oleh Sang Buddha. Ini kemudian dikenal sebagai garudhamma, dan mereka menggambarkan hubungan subordinat dari komunitas bhikkhunī dengan bikkhu atau biksu.[44][42] Cendekiawan kepercayaan-kepercayaan Asia Reiko Ohnuma berpendapat bahwa hutang Sang Buddha terhadap ibu angkatnya Mahāpajāpatī mungkin menjadi alasan utama untuk konsesinya sehubungan dengan pembentukan ordo bhikkhunī.[45]
Banyak cendekiawan menafsirkan kisah ini berarti bahwa Sang Buddha enggan mengizinkan wanita untuk ditahbiskan, dan bahwa Ānanda berhasil membujuk Sang Buddha untuk mengubah pikirannya. Misalnya, Indolog dan penerjemah I.B. Horner menulis bahwa "ini adalah satu-satunya contoh [Buddha]-nya terlalu dibujuk dalam argumen".[46] Namun, beberapa sarjana menafsirkan penolakan awal Sang Buddha lebih sebagai ujian tekad, mengikuti pola yang tersebar luas dalam Kanon Pāli dan dalam prosedur monastik yang mengulangi permintaan tiga kali sebelum penerimaan akhir.[47][48] Beberapa juga berpendapat bahwa Buddha diyakini oleh umat Buddha sebagai mahatahu, dan karena itu tidak mungkin digambarkan berubah pikiran. Cendekiawan lain berpendapat bahwa bagian-bagian lain dalam teks-teks menunjukkan bahwa Sang Buddha selama ini bermaksud untuk mendirikan suatu tatanan bhikkhunī.[46] Bagaimanapun, selama penerimaan wanita ke dalam ordo monastik, Sang Buddha memberi tahu Ānanda bahwa Ajaran Sang Buddha akan bertahan lebih pendek karena hal ini.[49][44] Pada saat itu, ordo monastik Buddhis terdiri dari laki-laki selibat yang berkeliaran, tanpa banyak institusi monastik. Membiarkan wanita untuk bergabung dengan kehidupan selibat Buddhis mungkin telah menyebabkan pertikaian, serta godaan di antara kedua jenis.[50] Namun, garudhamma dimaksudkan untuk memperbaiki masalah ini, dan mencegah dispensasi dibatasi.[51]
Ada beberapa perbedaan kronologis dalam catatan tradisional tentang pembentukan tatanan bhikkhunī. Menurut tradisi tekstual Pāli dan Mahīśasaka, tarekat bhikkhunī didirikan lima tahun setelah pencerahan Sang Buddha, tetapi, menurut sebagian besar tradisi tekstual, Ānanda hanya menjadi pelayan dua puluh tahun setelah pencerahan Sang Buddha. Lebih jauh lagi, Mahāpajāpatī adalah ibu angkat Sang Buddha, dan karena itu pasti jauh lebih tua darinya. Namun, setelah ordo bhikkhunī didirikan, Mahāpajāpatī masih memiliki banyak audiensi dengan Sang Buddha, seperti yang dilaporkan dalam Pāli dan Teks Buddhis Awal Tionghoa. Karena alasan ini dan alasan lainnya, dapat disimpulkan bahwa pembentukan tatanan bhikkhunī sebenarnya terjadi awal dalam pelayanan Sang Buddha. Jika demikian halnya, peran Ānanda dalam membangun tatanan menjadi kurang mungkin. Oleh karena itu, beberapa sarjana menafsirkan nama-nama dalam catatan tersebut, seperti Ānanda dan Mahāpajāpatī, sebagai simbol, mewakili kelompok daripada individu tertentu.[47]
Menurut teks, peran Ānanda dalam mendirikan ordo bhikkhunī membuatnya populer di komunitas bhikkhunī. Ānanda sering mengajarkan bhikkhunī,[2][52] sering mendorong wanita untuk ditahbiskan, dan ketika dia dikritik oleh biksu Mahākassapa, beberapa bhikkhunī mencoba membelanya.[53][54] Menurut Indolog Oskar von Hinüber, sikap nanda yang pro-bhikkhunī mungkin menjadi alasan mengapa sering terjadi diskusi antara Ānanda dan Mahākassapa, akhirnya memimpin Mahākassapa untuk mendakwa Ānanda dengan beberapa pelanggaran selama Sidang Buddhis Pertama. Von Hinüber lebih lanjut berpendapat bahwa pembentukan tatanan bhikkhunī mungkin telah dimulai dengan baik oleh Ānanda setelah kematian Sang Buddha, dan pengenalan Mahāpajāpatī sebagai orang yang meminta untuk melakukannya hanyalah alat sastra untuk menghubungkan penahbisan wanita dengan pribadi Sang Buddha, melalui ibu angkatnya. Von Hinüber menyimpulkan ini berdasarkan beberapa pola dalam teks-teks awal, termasuk jarak yang tampak antara Sang Buddha dan ordo bhikkhunī, dan seringnya diskusi dan perbedaan pendapat yang terjadi antara Ānanda dan Mahākassapa.[55] Beberapa cendekiawan telah melihat manfaat dalam argumen von Hinüber sehubungan dengan pro dan anti faksi,[56][57] tetapi pada tahun 2017, tidak ada bukti definitif yang ditemukan untuk teori pendirian tarekat bhikkhunī setelah kematian Sang Buddha.[58] Sarjana studi Buddhis Bhikkhu Anālayo telah menanggapi sebagian besar argumen von Hinuber, dengan menulis: "Selain membutuhkan terlalu banyak asumsi, hipotesis ini bertentangan dengan hampir 'semua bukti yang disimpan dalam teks bersama-sama'",[note 3] berargumen bahwa disiplin monastiklah yang menciptakan jarak antara Sang Buddha dan para bhikkhunī, dan meskipun demikian, ada banyak tempat dalam teks-teks awal di mana Sang Buddha berbicara langsung dengan bhikkhunī.[59]
Kematian Sang Buddha
suntingTerlepas dari pergaulannya yang lama dan kedekatannya dengan Sang Buddha, teks-teks menggambarkan bahwa Ānanda belum mencapai pencerahan. Karena itu, sesama biksu Udāyī (bahasa Sanskerta: Udāyin) mengejek Ānanda. Namun, Sang Buddha menegur Udāyī sebagai tanggapan, dengan mengatakan bahwa Ānanda pasti akan tercerahkan dalam kehidupan ini.[60][note 4]
Pāli Mahā-parinibbāna Sutta menceritakan perjalanan panjang tahun terakhir yang dilakukan Sang Buddha bersama Ānanda dari Rājagaha (bahasa Sanskerta: Rājagṛha) ke kota kecil Kusināra (bahasa Sanskerta: Kuśingarī) sebelum Sang Buddha meninggal di sana. Sebelum mencapai Kusināra, Sang Buddha melakukan pertapaan selama musim hujan (bahasa Pali: vassa, bahasa Sanskerta: varṣā) di Veḷugāma (bahasa Sanskerta: Veṇugrāmaka), keluar dari daerah Vesālī yang menderita kelaparan.[61] Di sini, Buddha berusia delapan puluh tahun mengungkapkan keinginannya untuk berbicara dengan saṅgha sekali lagi.[61] Sang Buddha sakit parah di Vesālī, yang membuat beberapa muridnya khawatir.[62] Ānanda mengerti bahwa Sang Buddha ingin meninggalkan instruksi terakhir sebelum kematiannya. Sang Buddha menyatakan, bagaimanapun, bahwa Beliau telah mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan, tanpa menyembunyikan rahasia apapun seperti yang akan dilakukan oleh seorang guru dengan "kepalan tertutup". Dia juga memberi kesan kepada Ānanda bahwa dia tidak berpikir saṅgha harus terlalu bergantung pada seorang pemimpin, bahkan dirinya sendiri.[63][64] Dia kemudian melanjutkan dengan pernyataan terkenal untuk mengambil ajarannya sebagai perlindungan, dan diri sendiri sebagai perlindungan, tanpa bergantung pada perlindungan lain, juga setelah dia pergi.[65][66] Bareau berpendapat bahwa ini adalah salah satu bagian teks yang paling kuno, ditemukan dalam sedikit variasi dalam lima tradisi tekstual awal:
“Lagi pula, episode yang sangat indah ini, menyentuh dengan keluhuran dan ketegasan psikologis sehubungan dengan Ānanda dan Buddha, tampaknya kembali sangat jauh, pada saat para penulis, seperti para siswa lainnya, masih menganggap Yang Terberkahi [Buddha] seorang manusia, seorang guru yang sangat terhormat dan tidak ternoda, kepada siapa perilaku dan kata-kata yang sepenuhnya manusiawi dipinjamkan, sehingga seseorang bahkan tergoda untuk melihat di sana ingatan akan adegan nyata yang dilaporkan Ānanda diceritakan kepada Komunitas di bulan-bulan setelah Parinirvāṇa [kematian Sang Buddha]."[67]
Teks yang sama berisi kisah di mana Sang Buddha, dalam banyak kesempatan, memberi petunjuk bahwa dia bisa memperpanjang hidupnya hingga satu kalpa penuh melalui pencapaian supranatural, tapi ini adalah kekuatan yang harus diminta untuk dia gunakan.[68][note 5] Ānanda terganggu, bagaimanapun, dan tidak menerima petunjuk itu. Kemudian, Ānanda membuat permintaan, tetapi Sang Buddha menjawab bahwa itu sudah terlambat, karena dia akan segera mati.[66][70] Māra, personifikasi Buddhis dari kejahatan, telah mengunjungi Sang Buddha, dan Sang Buddha telah memutuskan untuk mati dalam tiga bulan.[71] Ketika Ānanda mendengar ini, dia menangis. Sang Buddha menghiburnya, bagaimanapun, menunjukkan bahwa Ānanda telah menjadi pelayan yang hebat, peka terhadap kebutuhan orang yang berbeda.[2] Jika dia sungguh-sungguh dalam usahanya, dia akan segera mencapai pencerahan.[8] Dia kemudian menunjukkan kepada Ānanda bahwa semua hal yang berkondisi tidak kekal: semua orang harus mati.[72][note 6]
Pada hari-hari terakhir kehidupan Sang Buddha, Sang Buddha melakukan perjalanan ke Kusināra.[73] Sang Buddha menyuruh Ānanda menyiapkan tempat untuk berbaring di antara dua pohon sal, jenis pohon yang sama di mana ibu Buddha melahirkan.[74] Sang Buddha kemudian meminta Ānanda mengundang klan Malla dari Kusināra untuk memberikan penghormatan terakhir mereka.[75][76] Setelah kembali, Ānanda bertanya kepada Sang Buddha apa yang harus dilakukan dengan tubuhnya setelah kematiannya, dan dia menjawab bahwa itu harus dikremasi, memberikan instruksi rinci tentang bagaimana ini harus dilakukan.[66] Karena Sang Buddha melarang Ānanda untuk terlibat sendiri, melainkan menyuruhnya menginstruksikan Malla untuk melakukan ritual, instruksi ini oleh banyak sarjana ditafsirkan sebagai larangan bahwa monastik tidak boleh terlibat dalam pemakaman atau pemujaan stūpa (struktur dengan peninggalan). Sarjana studi Buddhis Gregory Schopen telah menunjukkan, bagaimanapun, bahwa larangan ini hanya berlaku untuk Ānanda, dan hanya berkaitan dengan upacara pemakaman Sang Buddha.[77][78] Juga telah ditunjukkan bahwa instruksi pada pemakaman berasal dari sangat terlambat, dalam komposisi dan penyisipan ke dalam teks, dan tidak ditemukan dalam teks-teks paralel, selain dari Mahāparinibbāna Sutta.[79] Ānanda kemudian melanjutkan dengan menanyakan bagaimana para penyembah harus menghormati Sang Buddha setelah kematiannya. Sang Buddha menanggapinya dengan menyebutkan empat tempat penting dalam hidupnya yang dapat dikunjungi oleh orang-orang, yang kemudian menjadi empat tempat utama ziarah umat Buddha.[80][63] Sebelum Sang Buddha meninggal, Ānanda merekomendasikan Sang Buddha untuk pindah ke kota yang lebih berarti sebagai gantinya, tetapi Sang Buddha menunjukkan bahwa kota itu pernah menjadi ibu kota yang besar.[73] Ānanda kemudian bertanya siapa yang akan menjadi guru berikutnya setelah Sang Buddha pergi, tetapi Sang Buddha menjawab bahwa ajaran dan disiplinnya akan menjadi guru sebagai gantinya.[66] Ini berarti bahwa keputusan harus dibuat dengan mencapai konsensus dalam saṅgha.,[81] dan secara lebih umum, bahwa sekarang saatnya telah tiba bagi para biarawan dan penyembah Buddhis untuk mengambil teks-teks Buddhis sebagai otoritas, sekarang Sang Buddha sedang sekarat.[82]
Sang Buddha memberikan beberapa instruksi sebelum kematiannya, termasuk arahan dari mantan kusirnya, Channa (bahasa Sanskerta: Chandaka) dijauhi oleh sesama bhikkhu, untuk merendahkan harga dirinya.[63] Di saat-saat terakhirnya, Sang Buddha bertanya apakah ada orang yang memiliki pertanyaan yang ingin mereka ajukan kepadanya, sebagai kesempatan terakhir untuk menghilangkan keraguan. Ketika tidak ada yang menjawab, Ānanda mengungkapkan kegembiraan bahwa semua siswa Buddha yang hadir telah mencapai tingkat yang melampaui keraguan tentang ajaran Buddha. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa Ānanda berbicara karena keyakinan dan bukan karena pandangan terang meditatif—sebuah celaan terakhir.[83] Sang Buddha menambahkan bahwa, dari semua lima ratus bhikkhu yang mengelilinginya sekarang, bahkan yang "terbaru" atau "paling terbelakang" (bahasa Pali: pacchimaka) telah mencapai tahap awal sotapanna. Dimaksudkan sebagai dorongan, Sang Buddha mengacu pada Ānanda.[84] Selama Nirwana terakhir Sang Buddha, Anuruddha mampu menggunakan kekuatan meditasinya untuk memahami tahap mana yang dilalui Buddha sebelum mencapai Nirwana akhir. Namun, Ānanda tidak dapat melakukannya, menunjukkan kematangan spiritualnya yang lebih rendah.[85] Setelah kematian Sang Buddha, Ānanda membacakan beberapa syair, mengungkapkan rasa urgensi (bahasa Pali: saṃvega), sangat tersentuh oleh peristiwa dan pengaruhnya: "Mengerikan adalah gempa, rambut pria berdiri, / Ketika Buddha yang sempurna meninggal dunia."[86]
Tak lama setelah sidang, Ānanda membawa pesan sehubungan dengan arahan Sang Buddha kepada Channa secara pribadi. Channa direndahkan dan diubah jalannya, mencapai pencerahan, dan hukumannya ditarik oleh saṅgha.[87][88] Ānanda pergi ke Sāvatthī (bahasa Sanskerta: Śrāvastī), di mana dia bertemu dengan penduduk yang sedih, yang dia hibur dengan ajaran tentang ketidakkekalan. Setelah itu, Ānanda pergi ke tempat tinggal Sang Buddha dan melakukan gerakan rutin yang sebelumnya ia lakukan ketika Sang Buddha masih hidup, seperti menyiapkan air dan membersihkan tempat tinggal. Dia kemudian memberi hormat dan berbicara ke tempat seolah-olah Sang Buddha masih ada di sana. Komentar Pāli menyatakan bahwa Ānanda melakukan ini karena pengabdian, tetapi juga karena dia "belum bebas dari nafsu".[89]
Sidang Pertama
suntingLarangan
suntingMenurut teks, Sidang Buddhis Pertama diadakan di Rājagaha.[90] Dalam vassa pertama setelah kematian Sang Buddha, biksu ketua Mahākassapa (bahasa Sanskerta: Mahākāśyapa) memanggil Ānanda untuk membacakan khotbah-khotbah yang telah didengarnya, sebagai wakil dari dewan ini.[7][90][note 7] Ada aturan yang dikeluarkan bahwa hanya murid yang tercerahkan (arahant) yang diizinkan untuk menghadiri sidang, untuk mencegah penderitaan mental mengaburkan ingatan para murid. Bagaimanapun, Ānanda belum mencapai pencerahan, berbeda dengan para anggota sidang lainnya, yang terdiri dari 499 arahant.[92][93] Oleh karena itu Mahākassapa belum mengizinkan Ānanda untuk hadir. Meskipun dia tahu bahwa kehadiran Ānanda di dewan diperlukan, dia tidak ingin berprasangka buruk dengan mengizinkan pengecualian terhadap aturan tersebut.[16][94] Tradisi Mūlasarvāstivāda menambahkan bahwa Mahākassapa pada awalnya mengizinkan Ānanda untuk bergabung sebagai semacam pelayan yang membantu selama dewan, tetapi kemudian dipaksa untuk menyingkirkannya ketika murid Anuruddha melihat bahwa Ānanda belum tercerahkan.[16]
Ānanda merasa terhina, tetapi didorong untuk memfokuskan upayanya untuk mencapai pencerahan sebelum sidang dimulai.[95][96] Teks-teks Mūlasarvāstivāda menambahkan bahwa dia merasa termotivasi ketika dia mengingat kata-kata Sang Buddha bahwa dia harus menjadi perlindungannya sendiri, dan ketika dia dihibur dan dinasihati oleh Anuruddha dan Vajjiputta, yang terakhir menjadi pelayannya.[16] Pada malam sebelum acara, ia berusaha keras untuk mencapai pencerahan. Setelah beberapa saat, Ānanda beristirahat dan memutuskan untuk berbaring untuk beristirahat. Dia kemudian mencapai pencerahan di sana, saat itu juga, di tengah jalan antara berdiri dan berbaring. Dengan demikian, Ānanda dikenal sebagai murid yang mencapai pencerahan "tidak satu pun dari empat pose tradisional" (berjalan, berdiri, duduk, atau berbaring).[97][98] Keesokan paginya, untuk membuktikan pencerahannya, Ānanda melakukan pencapaian supranatural dengan menyelam ke dalam bumi dan muncul di kursinya di dewan (atau, menurut beberapa sumber, dengan terbang di udara).[16] Cendekiawan seperti Buddhologis André Bareau dan sarjana agama Ellison Banks Findly telah skeptis tentang banyak detail dalam akun ini, termasuk jumlah peserta dewan, dan kisah pencerahan Ānanda sebelum dewan.[99] Bagaimanapun, hari ini, kisah perjuangan Ānanda pada malam sebelum sidang masih diceritakan di kalangan umat Buddhis sebagai nasihat dalam praktik meditasi: tidak menyerah, atau menafsirkan latihan terlalu kaku.[98]
Pembacaan
suntingSidang Pertama dimulai ketika Ānanda dimintai pendapat untuk melafalkan khotbah-khotbah dan untuk menentukan mana yang otentik dan mana yang tidak.[100][101] Mahākassapa menanyakan setiap khotbah yang Ānanda sebutkan di mana, kapan, dan kepada siapa khotbah itu diberikan,[2][102] dan di akhir pertemuan ini, majelis sepakat bahwa ingatan dan bacaan Ānanda benar,[103] setelah itu kumpulan wacana (bahasa Pali: Sutta Piṭaka, bahasa Sanskerta: Sūtra Piṭaka) dianggap selesai dan ditutup.[101] Oleh karena itu Ānanda memainkan peran penting dalam dewan ini,[6] dan teks mengklaim dia mengingat 84.000 topik pengajaran, di antaranya 82.000 diajarkan oleh Sang Buddha dan 2.000 lainnya diajarkan oleh para siswa.[104][105][note 8] Banyak khotbah Buddhis awal dimulai dengan kata-kata "Demikianlah yang telah saya dengar" (bahasa Pali: Evaṃ me sutaṃ, bahasa Sanskerta: Evaṃ mayā śrutam), yang menurut sebagian besar tradisi Buddhis, adalah kata-kata Ānanda,[106][note 9] menunjukkan bahwa dia, sebagai orang yang melaporkan teks (bahasa Sanskerta: saṃgītikāra), memiliki pengalaman langsung dan tidak menambahkan apa pun ke dalamnya.[108][109] Demikianlah, khotbah-khotbah yang diingat Ānanda kemudian menjadi kumpulan khotbah-khotbah Kanon,[7] dan menurut tradisi tekstual Haimavāta, Dharmaguptaka dan Sarvāstivāda (dan secara implisit, kronik Pāli pasca-kanonik), kumpulan Abhidhamma (Abhidhamma Piṭaka) juga.[104][91][110] Sarjana agama Ronald Davidson mencatat, bagaimanapun, bahwa ini tidak didahului oleh catatan Ānanda belajar Abhidhamma.[111] Menurut beberapa catatan Mahāyāna kemudian, Ānanda juga membantu melafalkan teks-teks Mahāyāna, yang diadakan di tempat yang berbeda di Rājagaha, tetapi dalam periode waktu yang sama.[112][113] Komentar Pāli menyatakan bahwa setelah sidang, ketika tugas membaca dan menghafal teks-teks dibagi, Ānanda dan murid-muridnya diberi tugas untuk mengingat Dīgha Nikāya.[16][110]
Tuduhan
suntingSelama dewan yang sama, Ānanda didakwa melakukan pelanggaran oleh anggota saṅgha karena memungkinkan wanita untuk bergabung dengan ordo monastik.[114][100] Selain itu, ia didakwa karena lupa meminta Sang Buddha untuk menentukan pelanggaran disiplin monastik mana yang dapat diabaikan;[note 10] karena telah menginjak jubah Buddha; karena telah mengizinkan wanita untuk menghormati tubuh Buddha setelah kematiannya, yang tidak berpakaian dengan benar, dan di mana tubuhnya dinodai oleh air mata mereka; dan karena gagal meminta Sang Buddha untuk terus hidup. Ānanda tidak mengakui ini sebagai pelanggaran, tetapi dia tetap melakukan pengakuan formal, "... dengan keyakinan akan pendapat para bhikkhu senior yang terhormat"[115][116]—Ānanda ingin mencegah gangguan dalam saṅgha.[117] Sehubungan dengan penahbisan wanita, Ānanda menjawab bahwa dia telah melakukan ini dengan susah payah, karena Mahāpajāpati adalah ibu angkat Sang Buddha yang telah lama menafkahinya.[118] Sehubungan dengan tidak meminta Sang Buddha untuk terus hidup, banyak tradisi tekstual memiliki tanggapan Ānanda dengan mengatakan bahwa ia terganggu oleh Māra,[119] meskipun satu teks Tiongkok awal memiliki jawaban Ānanda dia tidak meminta Sang Buddha untuk memperpanjang hidupnya, karena takut hal ini akan mengganggu pelayanan Buddha Maitreya berikutnya.[120]
Menurut tradisi Pāli, tuntutan diberikan setelah Ānanda mencapai pencerahan dan melakukan semua pelafalan; tetapi tradisi Mūlasarvāstivāda mengatakan bahwa tuduhan itu diajukan sebelum Ānanda menjadi tercerahkan dan memulai pelafalan. Dalam versi ini, ketika Ānanda mendengar bahwa dia dilarang dari dewan, dia berkeberatan bahwa dia tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan ajaran dan disiplin Sang Buddha. Mahākassapa kemudian membuat daftar tujuh tuntutan untuk melawan keberatan Ānanda. Tuduhan itu serupa dengan lima tuduhan yang diberikan dalam Pāli.[16] Tradisi tekstual lainnya mencantumkan tuduhan yang sedikit berbeda, berjumlah total gabungan sebelas tuduhan, beberapa di antaranya hanya disebutkan dalam satu atau dua tradisi tekstual.[121] Menimbang bahwa seorang siswa yang tercerahkan terlihat telah mengatasi semua kesalahan, tampaknya lebih mungkin tuduhan itu diajukan sebelum pencapaian Ānanda daripada sesudahnya.[120]
Indolog von Hinüber dan Jean Przyluski berpendapat bahwa Ānanda didakwa dengan pelanggaran selama sidang menunjukkan ketegangan antara sekolah-sekolah Buddhis awal yang bersaing, yaitu sekolah-sekolah yang menekankan wacana (bahasa Pali: sutta, bahasa Sanskerta: sūtra) dan sekolah yang menekankan disiplin monastik. Perbedaan-perbedaan ini telah mempengaruhi kitab suci masing-masing tradisi: misalnya tradisi tekstual Pāli dan Mahīśāsaka menggambarkan seorang Mahākassapa yang lebih kritis terhadap Ānanda daripada yang digambarkan oleh tradisi Sarvāstivāda,[57][122] mencerminkan preferensi untuk disiplin di atas wacana pada bagian dari tradisi sebelumnya, dan preferensi untuk wacana untuk yang terakhir.[123] Contoh lainnya adalah bacaan-bacaan selama Sidang Pertama. Teks-teks Pāli menyatakan bahwa Upāli, orang yang bertanggung jawab atas pembacaan disiplin monastik, dibacakan sebelum Ānanda melakukan: lagi, disiplin monastik di atas wacana.[124] Menganalisis enam resensi tradisi tekstual yang berbeda dari Mahāparinibbāna Sutta secara ekstensif, Bareau membedakan dua lapisan dalam teks, yang lebih tua dan yang lebih baru, yang pertama milik penyusun yang menekankan wacana, yang terakhir dengan yang menekankan disiplin; yang pertama menekankan sosok Ānanda, yang terakhir Mahākassapa. Dia lebih lanjut berpendapat bahwa bagian tentang Māra yang menghalangi Sang Buddha dimasukkan pada abad keempat SM, dan bahwa Ānanda disalahkan atas perbuatan Māra dengan menyisipkan bagian dari kelupaan Ānanda pada abad ketiga SM. Bagian di mana Sang Buddha sedang sakit dan mengingatkan Ānanda untuk menjadi tempat perlindungannya sendiri, di sisi lain, Bareau dianggap sangat kuno, mendahului bagian-bagian yang menyalahkan Māra dan Ānanda.[125] Sebagai kesimpulan, Bareau, Przyluski dan Horner berpendapat bahwa pelanggaran yang didakwakan kepada Ānanda adalah interpolasi kemudian. Namun, Findly tidak setuju, karena catatan dalam teks-teks disiplin monastik cocok dengan Mahāparinibbāna Sutta dan dengan karakter Ānanda seperti yang umumnya digambarkan dalam teks-teks.[126]
Historisitas
suntingTradisi menyatakan bahwa Sidang Pertama berlangsung selama tujuh bulan.[104] Namun, para sarjana meragukan apakah seluruh kanon benar-benar dibacakan selama Sidang Pertama,[127] karena teks-teks awal berisi kisah-kisah yang berbeda tentang subjek-subjek penting seperti meditasi.[128] Mungkin, meskipun demikian, versi-versi awal dibacakan dari apa yang sekarang dikenal sebagai Vinaya-piṭaka dan Sutta-piṭaka.[129] Namun demikian, banyak sarjana, dari akhir abad ke-19 dan seterusnya, telah menganggap historisitas Sidang Pertama tidak mungkin. Beberapa sarjana, seperti orientalis Louis de La Vallée-Poussin dan D.P. Minayef, berpikir pasti ada pertemuan setelah kematian Sang Buddha, tetapi hanya mempertimbangkan karakter utama dan beberapa peristiwa sebelum atau sesudah Sidang Pertama sejarah.[87][130] Sarjana lain, seperti Bareau dan Indolog Hermann Oldenberg, menganggap mungkin bahwa catatan Sidang Pertama ditulis setelah Sidang Kedua, dan berdasarkan yang Kedua, karena tidak ada masalah besar yang harus dipecahkan setelah kematian Sang Buddha, atau kebutuhan lain untuk mengatur Dewan Pertama.[99][131] Banyak materi di akun, dan terlebih lagi di akun selanjutnya yang lebih berkembang, berurusan dengan Ānanda sebagai perantara yang tidak ternoda yang meneruskan ajaran Buddha yang sah.[132] Di sisi lain, arkeolog Louis Finot, Indolog E. E. Obermiller dan sampai batas tertentu Indolog Nalinaksha Dutt berpendapat bahwa Sidang Pertama adalah otentik, karena korespondensi antara teks Pāli dan tradisi Sanskerta.[133] Indolog Richard Gombrich, mengikuti argumen Bhikkhu Sujato dan Bhikkhu Brahmali, menyatakan bahwa "masuk akal untuk percaya ... bahwa sebagian besar Kitab Pāli memang melestarikan bagi kita Buddha-vacana, 'kata-kata Sang Buddha', ditransmisikan kepada kita melalui muridnya Ānanda dan Sidang Pertama".[134]
Peran dan karakter
sunting"Dia melayani Sang Buddha mengikutinya ke mana-mana seperti bayangan, membawakannya kayu gigi dan air, mencuci kakinya, menggosok tubuhnya, membersihkan selnya dan memenuhi semua tugasnya dengan sangat hati-hati. Pada siang hari, dia siap mencegah keinginan sekecil apa pun dari Sang Buddha. Pada malam hari, dengan tongkat dan obor di tangan, dia pergi sembilan kali mengelilingi sel Buddha dan tidak pernah meletakkannya karena dia akan tertidur dan gagal menjawab panggilan ke Sang Buddha."
diterjemahkan oleh Ellison Banks Findly, Manorathapūranī[135]
Ānanda diakui sebagai salah satu murid terpenting Sang Buddha.[136] Dalam daftar siswa yang diberikan dalam Aṅguttara Nikāya[note 11] dan Saṃyutta Nikāya, masing-masing siswa dinyatakan sebagai yang terdepan dalam beberapa kualitas. Ānanda disebutkan lebih sering daripada siswa lainnya: ia disebut paling terkemuka dalam perilaku, dalam perhatian kepada orang lain, dalam kekuatan ingatan, dalam pengetahuan dan dalam keteguhan hati.[5][137][138] Ānanda adalah subjek khotbah pujian yang disampaikan oleh Sang Buddha tepat sebelum kematian Sang Buddha, seperti yang dijelaskan dalam Mahāparinibbāna Sutta:[note 12] ini adalah khotbah tentang seorang pria yang baik hati, tidak egois, populer, dan bijaksana terhadap orang lain.[137] Dalam teks-teks ia digambarkan sebagai orang yang welas asih dalam hubungannya dengan umat awam, welas asih yang ia pelajari dari Sang Buddha.[139] Sang Buddha menyampaikan bahwa baik biksu maupun umat awam senang melihat Ānanda, dan senang mendengarnya melafalkan dan mengajarkan ajaran Buddha.[140][141] Selain itu, Ānanda dikenal karena keterampilan organisasinya, membantu Sang Buddha dengan tugas-tugas seperti sekretaris.[142] Dalam banyak hal, Ānanda tidak hanya melayani kebutuhan pribadi Sang Buddha, tetapi juga kebutuhan institut saṅgha yang masih muda dan berkembang.[143]
Apalagi karena kemampuannya mengingat banyak ajaran Sang Buddha, dia digambarkan sebagai yang terdepan dalam "setelah banyak mendengar" (bahasa Pali: bahussuta, bahasa Sanskerta: bahuśruta, Pinyin: Duowen Diyi).[21][144] Ānanda dikenal karena ingatannya yang luar biasa, yang penting dalam membantunya mengingat ajaran Buddha. Dia juga mengajar murid-murid lain untuk menghafal doktrin Buddhis. Karena alasan ini, Ānanda dikenal sebagai "Bendahara Dhamma" (bahasa Pali: Dhamma-bhaṇḍāgārika, bahasa Sanskerta: Dharma-bhaṇḍāgārika),[5][96] Dhamma (bahasa Sanskerta: Dharma) mengacu pada ajaran Buddha.[23] Menjadi orang yang telah menemani Sang Buddha sepanjang sebagian besar hidupnya, Ānanda dalam banyak hal merupakan ingatan hidup Sang Buddha, yang tanpanya saṅgha akan jauh lebih buruk.[96] Selain kemampuan ingatannya, Ānanda juga menonjol dalam hal itu, sebagai sepupu Sang Buddha, ia berani mengajukan pertanyaan langsung kepada Sang Buddha. Misalnya, setelah kematian Mahāvira dan konflik-konflik berikutnya yang digambarkan di antara komunitas Jain, Ānanda bertanya kepada Sang Buddha bagaimana masalah seperti itu dapat dicegah setelah kematian Sang Buddha.[145][146][note 13] Namun, Findly berpendapat bahwa tugas Ānanda untuk menghafal ajaran Buddha secara akurat dan tanpa distorsi, adalah "baik hadiah maupun beban". Ānanda dapat mengingat banyak khotbah kata demi kata, tetapi ini juga berjalan seiring dengan kebiasaan untuk tidak merenungkan ajaran-ajaran itu, takut bahwa refleksi mungkin mendistorsi ajaran saat dia mendengarnya.[148] Pada beberapa kesempatan, Ānanda diperingatkan oleh murid-murid lain bahwa ia harus menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berbicara dengan umat awam, dan lebih banyak waktu untuk berlatih sendiri. Meskipun Ānanda secara teratur berlatih meditasi selama berjam-jam, ia kurang berpengalaman dalam konsentrasi meditatif dibandingkan murid-murid terkemuka lainnya.[149] Dengan demikian, penilaian karakter Ānanda tergantung pada apakah seseorang menilai pencapaiannya sebagai seorang bhikkhu atau pencapaiannya sebagai seorang pelayan, dan orang yang menghafal khotbah.[148]
Dari sudut pandang sastra dan pedagogis, Ānanda sering berfungsi sebagai semacam foil dalam teks, menjadi murid yang belum tercerahkan yang menghadiri seorang Buddha yang tercerahkan.[150][151] Karena orang yang biasa-biasa saja dapat mengidentifikasikan diri dengan Ānanda, Sang Buddha melalui Ānanda dapat menyampaikan ajarannya kepada massa dengan mudah.[150][152] Karakter Ānanda dalam banyak hal bertentangan dengan karakter Buddha: tidak tercerahkan dan seseorang yang melakukan kesalahan. Namun, pada saat yang sama, ia sepenuhnya mengabdikan diri untuk melayani Sang Buddha.[153] Sang Buddha digambarkan dalam teks-teks awal sebagai ayah dan guru bagi Ānanda, tegas tetapi penuh kasih. Ānanda sangat sayang dan terikat pada Sang Buddha, rela memberikan hidupnya untuknya.[21] Dia berduka atas kematian Buddha dan Sāriputta, yang dengannya dia menikmati persahabatan yang erat: dalam kedua kasus itu Ānanda sangat terkejut.[15] Keyakinan Ānanda pada Buddha, bagaimanapun, lebih merupakan keyakinan pada seseorang, terutama pribadi Sang Buddha, sebagai lawan dari keyakinan pada ajaran Buddha. Ini adalah pola yang muncul kembali dalam kisah-kisah yang mengarah pada pelanggaran yang dituduhkan oleh Ānanda selama Sidang Pertama.[154] Selain itu, kelemahan Ānanda yang dijelaskan dalam teks-teks adalah bahwa ia terkadang lamban dan kurang perhatian, yang menjadi nyata karena perannya sebagai pelayan Sang Buddha: ini melibatkan hal-hal kecil seperti deportasi, tetapi juga hal-hal yang lebih penting, seperti menahbiskan seorang pria tanpa masa depan sebagai murid, atau mengganggu Buddha pada waktu yang salah.[155] Misalnya, suatu kali Mahākassapa menghukum Ānanda dengan kata-kata yang keras, mengkritik fakta bahwa Ānanda bepergian dengan banyak biksu muda yang tampaknya tidak terlatih dan yang telah membangun reputasi buruk.[8] Dalam episode lain yang dijelaskan dalam teks Sarvāstivāda, Ānanda adalah satu-satunya siswa yang bersedia mengajarkan kekuatan batin kepada Devadatta, yang kemudian akan menggunakan ini dalam upaya untuk menghancurkan Sang Buddha. Akan tetapi, menurut sebuah teks Mahīśāsaka, ketika Devadatta telah berbalik melawan Sang Buddha, Ānanda tidak dibujuk olehnya, dan memberikan suara menentangnya dalam sebuah pertemuan formal.[156] Pertumbuhan spiritual Ānanda yang terlambat banyak dibahas dalam teks-teks Buddhis, dan kesimpulan umum adalah bahwa Ānanda lebih lambat dari murid lainnya karena keterikatan duniawinya dan keterikatannya pada pribadi Sang Buddha, keduanya berakar pada karya mediasinya antara Sang Buddha dan komunitas awam.[157]
Menyampaikan ajaran
suntingSetelah kematian Sang Buddha, beberapa sumber mengatakan Ānanda sebagian besar tinggal di India Barat, di daerah Kosambī (bahasa Sanskerta: Kausambī ), tempat dia mengajar sebagian besar muridnya.[158][9] Sumber lain mengatakan dia tinggal di vihara di Veḷuvana (bahasa Sanskerta: Veṇuvana).[159] Beberapa murid Ānanda menjadi terkenal dengan caranya sendiri. Menurut sumber-sumber Sanskerta pasca-kanonik seperti Divyavadāna dan Aśokavadāna, sebelum kematian Sang Buddha, Sang Buddha menceritakan kepada Ānanda bahwa murid terakhirnya, Majjhantika (bahasa Sanskerta: Madhyāntika) akan melakukan perjalanan ke Udyāna, Kashmir, untuk membawa ajaran Sang Buddha di sana.[160][161] Mahākassapa membuat prediksi yang nantinya akan menjadi kenyataan bahwa murid masa depan Ānanda lainnya, Sāṇavāsī (bahasa Sanskerta: Śāṇakavāsī, Śāṇakavāsin or Śāṇāvasika), akan memberikan banyak hadiah kepada saṅgha di Mathurā, selama pesta yang diadakan dari keuntungan bisnis yang sukses. Setelah peristiwa ini, Ānanda akan berhasil membujuk Sāṇavāsī untuk ditahbiskan dan menjadi muridnya.[162][163] Ānanda kemudian membujuk Sāṇavāsī dengan menunjukkan bahwa Sāṇavāsī sekarang telah memberikan banyak hadiah materi, tetapi tidak memberikan "pemberian Dhamma". Ketika dimintai penjelasan, Ānanda menjawab bahwa Sāṇavāsī akan memberikan hadiah Dhamma dengan ditahbiskan sebagai seorang bhikkhu, yang merupakan alasan yang cukup bagi Sāṇavāsī untuk membuat keputusan untuk ditahbiskan.[162]
Kematian dan relik
suntingĀnanda mengajar sampai akhir hayatnya.[7] Berdasarkan sumber Mūlasarvāstivāda, Ānanda mendengar seorang biksu muda melafalkan sebuah syair yang salah, dan menasehatinya. Ketika bhikkhu tersebut melaporkan hal ini kepada gurunya, gurunya keberatan bahwa "Ānanda telah menjadi tua dan ingatannya terganggu ..." Ini mendorong Ānanda untuk mencapai Nibbana akhir. Dia mewariskan "pemeliharaan doktrin [Buddha]" kepada muridnya Sāṇavāsī dan berangkat ke sungai Gangga.[164][165] Namun, menurut sumber Pāli, ketika Ānanda hampir meninggal, sebagai gantinya ia memutuskan untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya di Vesālī, dan pergi ke sungai Rohīni.[2] Versi Mūlasarvāstivāda memperluas dan mengatakan bahwa sebelum mencapai sungai, ia bertemu dengan seorang resi bernama Majjhantika (mengikuti ramalan sebelumnya) dan lima ratus pengikutnya, yang masuk agama Buddha.[4] Beberapa sumber menambahkan bahwa Ānanda menyampaikan pesan Buddha kepadanya.[162] Ketika nanda sedang menyeberangi sungai, dia diikuti oleh Raja Ajātasattu (bahasa Sanskerta: Ajātaśatrū), yang ingin menyaksikan kematiannya dan tertarik dengan jenazahnya sebagai relik.[4][2] Ānanda pernah berjanji kepada Ajāsattu bahwa dia akan memberi tahu dia kapan dia akan mati, dan karenanya, Ānanda telah memberitahunya.[166] Namun, di seberang sungai, sekelompok Licchavi dari Vesālī menunggunya untuk alasan yang sama. Dalam Pāli, ada juga dua pihak yang tertarik, tetapi pada sumber tersebut menyatakan kedua pihak tersebut adalah klan Sākiya dan Koliya.[4][2] Ānanda menyadari bahwa kematiannya di kedua sisi sungai dapat membuat marah salah satu pihak yang terlibat.[167] Melalui pencapaian supernatural, karena itu ia melonjak ke udara untuk melayang dan bermeditasi di udara, membuat tubuhnya terbakar, dengan reliknya mendarat di kedua tepi sungai,[4][2] atau dalam beberapa versi akun, terbelah menjadi empat bagian.[168] Dengan cara ini, Ānanda telah menyenangkan semua pihak yang terlibat.[4][2] Dalam beberapa versi lain dari kisah tersebut, termasuk versi Mūlasarvāstivāda, kematiannya terjadi di atas perahu di tengah sungai, bukan di udara. Jenazah dibagi menjadi dua, mengikuti keinginan Ānanda.[169][4]
Meskipun tidak ada Teks Buddhis Awal yang memberikan tanggal kematian Ānanda, menurut biksu peziarah Cina Faxian (337–422 CE), Ānanda terus hidup hingga 120 tahun.[2] Namun, mengikuti garis waktu selanjutnya, Ānanda mungkin hidup sampai 75–85 tahun.[158] Sarjana bidang studi Buddha L. S. Cousins memperkirakan tanggal kematian Ānanda adalah dua puluh tahun setelah Sang Buddha.[170] Dalam Teks Buddhis Awal, Ānanda telah mencapai Nirwana akhir dan tidak akan terlahir kembali. Tetapi, berbeda dengan teks-teks awal, menurut Sūtra Teratai Mahāyāna, Ānanda akan lahir sebagai Buddha di masa depan. Dia akan mencapai tujuannya lebih lambat dari Buddha saat ini, Buddha Gautama, karena Ānanda bercita-cita menjadi seorang Buddha dengan menerapkan proses "pembelajaran bagus". Namun, karena jalan yang panjang dan upaya yang besar ini, pencerahannya akan menjadi luar biasa dan dengan kemegahan yang luar biasa.[4]
Sampai akhir hayatnya, Ananda mengajarkan Dharma.[171] Menurut sumber-sumber Mulasarvativada, setelah mendengar bhikkhu muda itu salah membaca syair itu, nanda mengoreksinya. Bhikkhu itu melaporkan hal ini kepada gurunya, dan gurunya keberatan bahwa "Ananda menjadi tua dan ingatannya memburuk ..." Hal ini mendorong Ananda untuk mencapai parinirvana. Dia menyerahkan otoritas kepada muridnya Sanavasa dan pergi ke Sungai Gangga.[172][173] Menurut sumber Pali, merasa bahwa hidup akan segera berakhir, dia, seperti Sang Buddha, memutuskan untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya di Vesali dan berangkat dari Rajagahi ke Sungai Rohini.[174] Versi Mulasarvastivada yang lebih rinci mengatakan bahwa sebelum mencapai sungai, ia diprediksi akan bertemu dengan Resi Majhantika dan lima ratus pengikutnya, yang telah memeluk agama Buddha.[173] Beberapa sumber menambahkan bahwa nanda memberinya pesan Sang Buddha.[173][175] Ketika Ananda menyeberangi sungai, ia diikuti oleh Raja Ajatasatru. (Skt. Ajātaśatr), yang ingin menyaksikan kematiannya dan menerima jenazahnya sebagai relik.[173][176] Di masa lalu, Ananda berjanji kepada Ajatasatru bahwa dia akan memperingatkannya tentang parinirvana dan menepati janjinya.[177] Di seberang sungai, untuk alasan yang sama, sekelompok perwakilan dari klan Lichchhavi dari Vesali sedang menunggunya. Menurut sumber Pali, ada juga pihak yang berkepentingan Shakiev dan Koliev.[173][176] Ananda menyadari bahwa kematiannya dapat menyebabkan perselisihan di antara orang-orang yang berkumpul. Oleh karena itu, dengan bantuan kemampuan supranatural, ia naik ke udara dan melarutkan tubuhnya dalam unsur api, dan jenazahnya mendarat di kedua tepi sungai[173][176] atau, menurut beberapa sumber, dibagi menjadi empat bagian.[175] Dengan demikian Ananda memuaskan semua pihak yang terkait[173][176] Menurut versi lain, termasuk Mulasarvativada, kematiannya terjadi di tengah sungai di dalam perahu, dan bukan di udara. Jenazah tersebut dibagi menjadi dua bagian sesuai dengan keinginan Ananda.[173]
Setelah kematian Ananda, para sesepuh melengkapi Theragatha dengan tiga kuatrain yang didedikasikan untuk parinirvana-nya, di mana mereka menyebut Ananda penjaga Dhamma, mata seluruh dunia dan sumber kebijaksanaan.[178] Murid terakhir Ananda, Majantika,[179] bersama dengan Sanavasa dan empat atau lima murid lainnya, membentuk mayoritas pada Sidang Buddhis Kedua.[179] Seorang murid Majantika adalah Upagupta, yang dianggap sebagai guru Kaisar Ashoka (abad ke-3 SM). Sumber-sumber Pali pasca-kanonik menyatakan bahwa Sanavasa memainkan peran utama dalam Sidang Buddhis Ketiga.[180] Meskipun kurangnya data sejarah, diyakini bahwa setidaknya salah satu tokoh utama dari Sidang Kedua adalah murid nanda, karena hampir semua tradisi tekstual menyebutkan hubungan dengan Ananda.
Dipercaya bahwa Raja Ajatasattu mendirikan stupa di atas relik Ananda. Menurut beberapa sumber, itu terletak di Sungai Rohini, dan menurut yang lain, di Sungai Gangga. Licchhavi juga membangun stupa di tepi sungai mereka.[181] Peziarah Cina Xuanzang (602-664) kemudian mengunjungi kedua stupa tersebut.[182][183] Faxian juga melaporkan bahwa dia melihat stupa dengan sisa-sisa Ananda di Sungai Rohini,[181] serta di Mathura.[184] Juga, menurut versi Sakmukta agama Mulasarvastivadin, Kaisar Ashoka tiba di lokasi dan memberikan persembahan paling mewah yang pernah dia berikan ke stupa.[185] Dia menjelaskan kedermawanan ini kepada para menterinya dengan mengatakan bahwa “tubuh Tathagata adalah tubuh Dharma, murni di alam. Dia [Ananda] mampu menjaga dia/mereka semua; karena alasan inilah persembahan [baginya] lebih unggul [dari semua yang lain]." Ungkapan "tubuh Dharma" di sini mengacu pada ajaran Buddha secara keseluruhan.[180]
Teks Buddhis awal menyatakan bahwa Ananda telah mencapai nirwana tertinggi dan tidak akan terlahir kembali. Menurut Sutra Teratai Mahayana, ia ditakdirkan untuk dilahirkan sebagai seorang Buddha. Dia memiliki jalan yang lebih panjang daripada Buddha Gotama, tetapi pencerahan akan menjadi luar biasa dan luar biasa.[185]
Warisan
suntingĀnanda digambarkan sebagai pembicara yang fasih, yang sering mengajarkan tentang diri dan tentang meditasi.[186] Ada banyak teks Buddhis yang dikaitkan dengan Ānanda, termasuk Atthakanāgara Sutta, tentang metode meditasi untuk mencapai Nirwana; sebuah versi dari Bhaddekaratta Sutta (bahasa Sanskerta: Bhadrakārātrī, Pinyin: shanye), tentang hidup di saat ini;[187][188] Sekha Sutta, tentang pelatihan yang lebih tinggi dari seorang siswa Buddha; Subha Suttanta, tentang praktik yang diilhami Buddha untuk diikuti orang lain.[189] Dalam Gopaka-Mogallānasutta, terjadi percakapan antara Ānanda, brahmana Gopaka-Mogallāna dan menteri Vassakara, yang terakhir adalah pejabat tertinggi wilayah Magadha.[190][191] Selama percakapan ini, yang terjadi tak lama setelah kematian Sang Buddha, Vassakara bertanya apakah sudah diputuskan siapa yang akan menggantikan Sang Buddha. Ānanda menjawab bahwa tidak ada penerus yang ditunjuk, tetapi komunitas Buddhis mengambil ajaran dan disiplin Buddha sebagai tempat perlindungan.[192][191] Selanjutnya, saṅgha tidak lagi memiliki Buddha sebagai guru, tetapi mereka akan menghormati para bhikkhu yang berbudi luhur dan dapat dipercaya.[191] Selain sutta-sutta ini, sebuah bagian dari Theragāthā dikaitkan dengan Ānanda.[193] Bahkan dalam teks-teks yang dikaitkan dengan Sang Buddha sendiri, nanda terkadang digambarkan memberi nama pada teks tertentu, atau menyarankan perumpamaan kepada Sang Buddha untuk digunakan dalam ajarannya.[8]
Dalam Buddhisme Asia Timur, Ānanda dianggap sebagai salah satu dari sepuluh murid utama.[194] Dalam banyak teks Sanskerta India dan Asia Timur, Ānanda dianggap sebagai patriark kedua dari garis keturunan yang mentransmisikan ajaran Buddha, dengan Mahākassapa sebagai yang pertama dan Majjhantika[195] atau Saṇavāsī[196] menjadi yang ketiga. Ada catatan yang berasal dari tradisi tekstual Sarvāstivāda dan Mūlasarvāstivāda yang menyatakan bahwa sebelum Mahākassapa meninggal, dia menganugerahkan ajaran Sang Buddha kepada Ānanda sebagai pewaris resmi otoritas, menyuruh nanda untuk meneruskan ajaran itu kepada murid Ānanda, Saṇavāsī.[197][198] Kemudian, tepat sebelum Ānanda meninggal, dia melakukan seperti yang diperintahkan Mahākassapa kepadanya.[16] Sarjana studi Buddhis Akira Hirakawa dan Bibhuti Baruah telah menyatakan skeptisisme tentang guru–hubungan siswa antara Mahākassapa dan Ānanda, dengan alasan bahwa ada perselisihan di antara keduanya, seperti yang ditunjukkan dalam teks-teks awal.[158][9] Terlepas dari itu, jelas dari teks-teks bahwa hubungan transmisi ajaran dimaksudkan, sebagai lawan dari upajjhāya–hubungan siswa dalam silsilah penahbisan: tidak ada sumber yang menunjukkan bahwa Mahākassapa adalah upajjhāya Ānanda.[199] Dalam ikonografi Mahāyāna, Ānanda sering digambarkan mengapit Sang Buddha di sisi kanan, bersama dengan Mahākassapa di kiri.[200] Namun, dalam ikonografi Theravāda, Ānanda biasanya tidak digambarkan dengan cara ini,[201] dan motif penyebaran Dhamma melalui daftar leluhur tidak ditemukan dalam sumber-sumber Pāli.[202]
Karena Ānanda berperan penting dalam mendirikan komunitas bhikkhunī, dia telah dihormati oleh bhikkhunīs untuk ini sepanjang sejarah Buddhis. Jejak paling awal dari ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan Faxian dan Xuan Zang,[53][203] yang melaporkan bahwa bhikkhunī memberikan persembahan kepada stūpa untuk menghormati nanda selama perayaan dan hari perayaan. Pada catatan yang sama, di Tiongkok abad ke-5–ke-6 dan Jepang abad ke-10, Teks-teks Buddhis disusun merekomendasikan wanita untuk menjunjung tinggi delapan sila semi-monastik untuk menghormati dan berterima kasih kepada Ānanda. Di Jepang, ini dilakukan melalui format ritual penebusan dosa yang disebut keka (Hanzi: 悔過). Pada abad ke-13, di Jepang minat kultus untuk Ānanda telah berkembang di sejumlah biara, di mana gambar dan stūpa digunakan dan upacara diadakan untuk menghormatinya. Saat ini, pendapat di antara para sarjana terbagi mengenai apakah pemujaan Ānanda di antara para bhikkhunī merupakan ekspresi ketergantungan mereka pada tradisi monastik laki-laki, atau sebaliknya, ekspresi legitimasi dan independensi mereka.[204]
Teks-teks Pāli Vinaya mengaitkan desain jubah biksu Buddha dengan Ānanda. Seiring berkembangnya Buddhisme, semakin banyak umat awam yang mulai menyumbangkan kain mahal untuk jubah, yang membuat para biksu berisiko dicuri. Untuk mengurangi nilai komersialnya, para bhikkhu memotong kain yang dipersembahkan, sebelum mereka menjahit jubah darinya. Sang Buddha meminta Ānanda untuk memikirkan model jubah Buddha, yang terbuat dari potongan-potongan kecil kain. Ānanda merancang model jubah standar, berdasarkan sawah Magadha, yang dibagi menjadi beberapa bagian oleh tepian tanah.[205][8] Tradisi lain yang terkait dengan Ānanda adalah pembacaan paritta. Umat Buddhis Theravāda menjelaskan bahwa kebiasaan memercikkan air selama nyanyian paritta berasal dari kunjungan Ānanda ke Vesālī, ketika dia melafalkan Ratana Sutta dan memercikkan air dari mangkuk dana makanannya.[31][206] Tradisi ketiga yang kadang-kadang dikaitkan dengan Ānanda adalah penggunaan pohon Bodhi dalam Buddhisme. Dijelaskan dalam teks Kāliṅgabodhi Jātaka bahwa nanda menanam pohon Bodhi sebagai simbol pencerahan Buddha, untuk memberi orang kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha.[8][207] Pohon dan kuil ini kemudian dikenal sebagai Pohon Bodhi Ānanda,[8] dikatakan telah tumbuh dari benih dari Pohon Bodhi asli di mana Buddha digambarkan telah mencapai pencerahan.[208] Banyak dari jenis kuil Pohon Bodhi di Asia Tenggara ini didirikan mengikuti contoh ini.[207] Saat ini, Pohon Bodhi Ānanda terkadang diidentikkan dengan sebuah pohon di reruntuhan Jetavana, Sāvatthi, berdasarkan catatan Faxian.[208]
Dalam seni
suntingAntara tahun 1856 dan 1858, Richard Wagner menulis draf untuk opera libretto berdasarkan legenda tentang Ānanda dan gadis kasta rendah Prakṛti. Dia hanya meninggalkan sketsa prosa yang terpisah-pisah dari sebuah karya yang disebut Die Sieger, tetapi topik itu mengilhami opera berikutnya Parsifal.[209] Selanjutnya, draft tersebut digunakan oleh komposer Jonathan Harvey dalam opera Wagner Dream 2007-nya.[210][211] Dalam legenda versi Wagner, yang didasarkan pada terjemahan orientalis Eugène Burnouf, mantra gaib ibu Prakṛti tidak bekerja pada Ānanda, dan Prakṛti menghadap Sang Buddha untuk menjelaskan keinginannya terhadap Ānanda. Sang Buddha menjawab bahwa penyatuan antara Prakṛti dan Ānanda adalah mungkin, tetapi Prakṛti harus menyetujui persyaratan Sang Buddha. Prakṛti setuju, dan terungkap bahwa Buddha memiliki maksud lain selain dia: ia meminta Prakṛti untuk ditahbiskan sebagai bhikkhunī, dan menjalani kehidupan selibat sebagai semacam saudara perempuan Ānanda. Pada awalnya, Prakṛti menangis karena cemas, tetapi setelah Sang Buddha menjelaskan bahwa situasinya saat ini adalah akibat dari karma dari kehidupan sebelumnya, dia memahami dan bergembira dalam kehidupan seorang bhikkhunī.[212] Terlepas dari tema spiritual, Wagner juga membahas kesalahan sistem kasta dengan meminta Buddha mengkritiknya.[209]
Menggambar dari filosofi Schopenhauer, Wagner membandingkan keselamatan yang didorong oleh keinginan dan keselamatan spiritual yang sejati: dengan mencari pembebasan melalui orang yang dia cintai, Prakṛti hanya menegaskan "keinginannya untuk hidup" (bahasa Jerman: Wille zum Leben), yang menghalanginya untuk mencapai pembebasan. Dengan ditahbiskan sebagai bhikkhunī, dia malah berjuang untuk keselamatan spiritualnya. Jadi, catatan Buddhis awal tentang penahbisan Mahāpajāpati digantikan oleh Prakṛti. Menurut Wagner, dengan membiarkan Prakṛti ditahbiskan, Sang Buddha juga menyelesaikan tujuan hidupnya sendiri: "Dia menganggap keberadaannya di dunia, yang tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi semua makhluk, sebagai selesai, karena dia telah mampu menawarkan pembebasan—tanpa mediasi—juga kepada wanita."[213]
Legenda yang sama tentang Ānanda dan Prakṛti dibuat menjadi drama prosa pendek oleh penyair India Rabindranath Tagore, yang disebut Chandalika. Chandalika membahas tema konflik spiritual, kasta dan kesetaraan sosial, dan berisi kritik keras terhadap masyarakat India. Sama seperti dalam kisah tradisional, Prakṛti jatuh cinta pada Ānanda, setelah dia memberikan harga dirinya dengan menerima hadiah air darinya. Ibu Prakṛti membacakan mantra untuk memikat Ānanda. Namun, dalam drama Tagore, Prakṛti kemudian menyesali apa yang telah dia lakukan dan mantranya dicabut.[214][215]
Catatan
sunting- ^ Menurut tradisi Mūlasarvāstivāda, Sang Buddha berusia 50.[11]
- ^ Menurut tradisi Mūlasarvāstivāda, Ānanda lahir pada saat yang sama ketika Sang Buddha menjadi tercerahkan, dan karena itu lebih muda dari para siswa terkemuka lainnya. Alasan mengapa murid-murid lain tidak dipilih mungkin karena mereka terlalu tua untuk tugas itu.
- ^ Anālayo cites von Hinüber with this phrase.
- ^ AN 3.80
- ^ There was some debate between the early Buddhist schools as to what eon means in this context, some schools arguing it meant a full human lifespan, others that an enlightened being was capable of producing a "new life-span by the sole power of his meditation".[69]
- ^ According to John Powers, the Buddha only left Vesālī at this point, and not earlier.[70]
- ^ This is the most well-known version of the account. However, the texts of the Sarvāstivāda, Mūlasarvāstivāda, and Mahīśāsaka traditions relate that this was Añña Koṇḍañña (bahasa Sanskerta: Ājñāta Kauṇḍinya) instead, as Koṇḍañña was the most senior disciple.[91]
- ^ Other sources say he remembered 60,000 words and 15,000 stanzas,[104] or 10,000 words.[106]
- ^ Some Mahāyāna commentators held that in some cases these were the words of a bodhisattva (someone striving to become a Buddha) like Mañjuśrī.[107]
- ^ The Buddha mentioned to Ānanda that "minor rules" could be abolished.[70]
- ^ Page i. xiv.
- ^ DN 16.
- ^ The Buddha responded with a discussion of the role of a teacher, a student and the teaching, and concluded that he himself had proclaimed his teaching well. He continued that disputes about monastic discipline were not so much a problem, but disputes about "the path and the way" were.[147]
Referensi
sunting- ^ a b c d e f g h Witanachchi 1965, hlm. 529.
- ^ a b c d e f g h i j k l m Buswell & Lopez 2013, Ānanda.
- ^ Larson, Paul. "Ananda". Dalam Leeming, David A.; Madden, Kathryn; Marlan, Stanton. Encyclopedia of Psychology and Religion. Springer-Verlag. hlm. 35. ISBN 978-0-387-71802-6.
- ^ a b c d e f g h Witanachchi 1965, hlm. 535.
- ^ a b c Sarao, K. T. S. (2004). "Ananda". Dalam Jestice, Phyllis G. Holy People of the World: A Cross-cultural Encyclopedia. ABC-CLIO. hlm. 49. ISBN 1-85109-649-3.
- ^ a b c Powers, John (2013). "Ānanda". A Concise Encyclopedia of Buddhism. Oneworld Publications. ISBN 978-1-78074-476-6.
- ^ a b c d e f g Keown 2004, hlm. 12.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Malalasekera 1960, Ānanda.
- ^ a b c Hirakawa 1993, hlm. 85.
- ^ Bareau, André (1988). "Les débuts de la prédication du Buddha selon l'Ekottara-Āgama" [The Beginning of the Buddha's Ministry According to the Ekottara Āgama]. Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient (dalam bahasa Prancis). 77 (1): 94. doi:10.3406/befeo.1988.1742.
- ^ a b Witanachchi 1965, hlm. 530.
- ^ a b c Witanachchi 1965, hlm. 529–30.
- ^ Shaw 2006, hlm. 35.
- ^ Findly 2003, hlm. 371–2.
- ^ a b Witanachchi 1965, hlm. 533.
- ^ a b c d e f g h Witanachchi 1965, hlm. 532.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Vajraputra.
- ^ Findly 2003, hlm. 372.
- ^ Findly 2003, hlm. 376.
- ^ Mcneill, William (2011). Berkshire Encyclopedia of World History (edisi ke-2nd). Berkshire Publishing Group. hlm. 270. ISBN 978-1-61472-904-4.
- ^ a b c Findly 2003, hlm. 375.
- ^ Malalasekera 1960, Nālāgiri.
- ^ a b Bodhi, Bhikkhu (2013). "Early Buddhist Disciples". Dalam Johnston, William M. Encyclopedia of Monasticism. Routledge. hlm. 389. ISBN 978-1-136-78716-4. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-09. Diakses tanggal 2022-07-13.
- ^ Findly 2003, hlm. 387.
- ^ Shaw 2006, hlm. 18.
- ^ Findly 2003, hlm. 368.
- ^ Findly 2003, hlm. 377.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Mallikā; Śyāmāvatī.
- ^ Bailey, Greg; Mabbett, Ian (2003). The Sociology of Early Buddhism (PDF). Cambridge University Press. hlm. 28. ISBN 978-0-511-06296-4. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 15 February 2017. Diakses tanggal 12 September 2018.
- ^ Findly 2003, hlm. 389–90.
- ^ a b Buswell & Lopez 2013, Ratanasutta.
- ^ Bodhi, Bhikkhu (2013). "Discourses". Dalam Johnston, William M. Encyclopedia of Monasticism. Routledge. hlm. 394. ISBN 978-1-136-78716-4. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-04-09. Diakses tanggal 2022-07-13.
- ^ Shaw 2006, hlm. 12.
- ^ Findly 2003, hlm. 375, 377.
- ^ Attwood, Jayarava (1 January 2008). "Did King Ajātasattu Confess to the Buddha, and did the Buddha Forgive Him?". Journal of Buddhist Ethics: 286. ISSN 1076-9005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 September 2018.
- ^ Ambros 2016, hlm. 243–4.
- ^ Wilson, Liz (1996). Charming Cadavers: Horrific Figurations of the Feminine in Indian Buddhist Hagiographic Literature. University of Chicago Press. hlm. 107–8. ISBN 978-0-226-90054-4.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Śūraṅgamasūtra.
- ^ Findly 2003, hlm. 379–80.
- ^ Violatti, Cristian (9 December 2013). "Siddhartha Gautama". World History Encyclopedia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 August 2014. Diakses tanggal 29 August 2018.
- ^ a b Ambros 2016, hlm. 241.
- ^ a b Ohnuma 2006, hlm. 862.
- ^ Ohnuma 2006, hlm. 872–3.
- ^ a b Hinüber 2007, hlm. 230–1.
- ^ Ohnuma 2006, hlm. 871.
- ^ a b Ohnuma 2006, hlm. 865.
- ^ a b Krey, Gisela (2014). "Some Remarks on the Status of Nuns and Laywomen in Early Buddhism". Dalam Mohr, Thea; Tsedroen, Jampa. Dignity and Discipline: Reviving Full Ordination for Buddhist Nuns. Simon and Schuster. ISBN 978-0-86171-830-6.
- ^ Ohnuma 2006, hlm. 865 n.9.
- ^ Jerryson, Michael (2013). "Buddhist Traditions and Violence". Dalam Juergensmeier, Mark; Kitts, Margo; Jerryson, Michael. The Oxford Handbook of Religion and Violence. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-975999-6.
- ^ Powers 2007, hlm. 53.
- ^ Raksachom, Krisana (2009). ปัญหาการตีความพระพุทธตำรัสต่อพระอานนท์หลังการบวชของพระนางมหาปชาบดีโคตมี [Problems in Interpreting the Buddha's Words to Ven. Ānanda after Ven. Mahāpajāpati Gotamī's Ordination] (PDF). Journal of Buddhist Studies, Chulalongkorn University (dalam bahasa Thai). 16 (3): 88. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 October 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Findly 2003, hlm. 384.
- ^ a b Ambros 2016, hlm. 209.
- ^ Hinüber 2007, hlm. 233–4.
- ^ Hinüber 2007, hlm. 235–7.
- ^ Ohnuma, Reiko (2013). "Bad Nun: Thullanandā in Pāli Canonical and Commentarial Sources" (PDF). Journal of Buddhist Ethics. 20: 51. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 1 October 2018.
- ^ a b Findly 1992, hlm. 253–4.
- ^ Muldoon-Hules, Karen (2017). Brides of the Buddha: Nuns' Stories from the Avadanasataka. Lexington Books. hlm. 4. ISBN 978-1-4985-1146-9.
- ^ Anālayo, Bhikkhu (2008). "Theories on the Foundation of the Nuns' Order: A Critical Evaluation" (PDF). Journal of the Centre for Buddhist Studies. 6: 125. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 September 2018.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Udāyin.
- ^ a b Buswell & Lopez 2013, Mahāparinibbānasuttanta; Veṇugrāmaka.
- ^ Powers 2007, hlm. 54.
- ^ a b c Buswell & Lopez 2013, Mahāparinibbānasuttanta.
- ^ Harvey 2013, hlm. 26.
- ^ Obeyesekere, Gananath (2017). "The Death of the Buddha: A Restorative Interpretation". The Buddha in Sri Lanka: Histories and Stories. Taylor & Francis. ISBN 978-1-351-59225-3.
- ^ a b c d Lopez 2017, hlm. 88.
- ^ Bareau 1979, hlm. 80:"En outre, cet épisode très beau, touchant de noblesse et de vraisemblance psychologique tant en ce qui regarde Ânanda qu'en ce qui concerne le Buddha, paraît bien remonter très loin, à l'époque où les auteurs, comme les autres disciples, considéraient encore le Bienheureux comme un homme, un maître éminemment respectable mais nullement divinisé, auquel on prêtait un comportement et des paroles tout à fait humaines, de telle sorte qu'on est même tenté de voir là le souvenir d'une scène réelle qu'Ânanda aurait racontée à la Communauté dans les mois qui suivirent le Parinirvâna."
- ^ Buswell & Lopez 2013, Māra.
- ^ Jaini, P. S. (1958). "Buddha's Prolongation of Life". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 21 (3): 547–8, 550. doi:10.1017/S0041977X0006016X.
- ^ a b c Powers 2007, hlm. 55.
- ^ Olson 2005, hlm. 33.
- ^ Hansen 2008, hlm. 45, 51.
- ^ a b Buswell & Lopez 2013, Kuśingarī.
- ^ Olson 2005, hlm. 34.
- ^ Warder, A. K. (2000). Indian Buddhism (PDF) (edisi ke-3rd). Motilal Banarsidass Publishers. ISBN 81-208-0818-5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 September 2015.
- ^ Ray 1994, hlm. 361.
- ^ Silk, Jonathan A. (2005) [2002]. "What, If Anything, Is Mahāyāna Buddhism?" (PDF). Dalam Williams, Paul. Buddhism: Critical Concepts in Religious Studies, 3: The Origins and Nature of Mahāyāna Buddhism. Routledge. hlm. 398. ISBN 0-415-33229-X. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 20 October 2015.
- ^ Ray 1994, hlm. 339, 359.
- ^ Bareau 1979, hlm. 67, 71, 73.
- ^ Lopez 2017, hlm. 3, 88–9.
- ^ Powers, John (2015). "Buddhas and Buddhisms". Dalam Powers, John. The Buddhist World. Routledge. ISBN 978-1-317-42016-3.
- ^ Ray 1994, hlm. 363–4.
- ^ Findly 1992, hlm. 256.
- ^ Freedman 1977, hlm. 26–7.
- ^ Ray 1994, hlm. 369, 392 n.80.
- ^ Hansen 2008, hlm. 53.
- ^ a b Prebish 2005, hlm. 226.
- ^ Mukherjee 1994, hlm. 466.
- ^ Strong, John S. (1977). ""Gandhakuṭī": The Perfumed Chamber of the Buddha". History of Religions. 16 (4): 398–9. doi:10.1086/462775. JSTOR 1062638.
- ^ a b c Thorp, Charley Linden (3 April 2017). "The Evolution of Buddhist Schools". World History Encyclopedia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 August 2018. Diakses tanggal 29 August 2018.
- ^ a b Prebish 2005, hlm. 230.
- ^ Powers 2007, hlm. 56.
- ^ Prebish 2005, hlm. 225–6.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Mahākāśyapa.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Īryāpatha; Mahākāśyapa.
- ^ a b c Filigenzi 2006, hlm. 271.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Ānanda; Īryāpatha.
- ^ a b Shaw 2006, hlm. 17–8.
- ^ a b Prebish 2005, hlm. 231.
- ^ a b Keown 2004, hlm. 164.
- ^ a b MacQueen 2005, hlm. 314.
- ^ Zurcher, Erik (2005). "Buddhist Influence on Early Taoism" (PDF). Dalam Williams, Paul. Buddhism: Critical Concepts in Religious Studies, 8: Buddhism in China, East Asia, and Japan. Routledge. hlm. 378. ISBN 0-415-33234-6. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 September 2018.
- ^ Powers 2007, hlm. 57–8.
- ^ a b c d Buswell & Lopez 2013, Council, 1st.
- ^ Lamotte 1988, hlm. 148.
- ^ a b Gwynne, Paul (2017). "Books". World Religions in Practice: A Comparative Introduction. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-97227-4.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Evaṃ mayā śrutam.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Saṃgītikāra.
- ^ Lamotte 2005a, hlm. 190.
- ^ a b Norman 1983, hlm. 8.
- ^ Davidson 1990, hlm. 305.
- ^ Lamotte 2005b, hlm. 256.
- ^ Davidson 1990, hlm. 308.
- ^ Chakravarti, Uma. The Social Dimensions of Early Buddhism. Munshiram Manoharlal Publishers.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Ānanda; Cāpālacaitya; Council, 1st.
- ^ Hinüber 2007, hlm. 235–6.
- ^ Freedman 1977, hlm. 470.
- ^ Ohnuma 2006, hlm. 867.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Cāpālacaitya.
- ^ a b Ch'en, Kenneth (1958). "The Mahāparinirvānasūtra and The First Council". Harvard Journal of Asiatic Studies. 21: 132. doi:10.2307/2718621. JSTOR 2718621.
- ^ Tsukamoto 1963, hlm. 820.
- ^ Tsukamoto 1963, hlm. 821.
- ^ Findly 1992, hlm. 254.
- ^ Freedman 1977, hlm. 487.
- ^ Bareau 1979, hlm. 70, 79–80.
- ^ Findly 1992, hlm. 268.
- ^ Harvey 2013, hlm. 88.
- ^ Gombrich, Richard (2006). How Buddhism Began: The Conditioned Genesis of the Early Teachings (edisi ke-2nd). Routledge. hlm. 96–7. ISBN 978-0-415-37123-0.
- ^ Hirakawa 1993, hlm. 69.
- ^ Mukherjee 1994, hlm. 453.
- ^ Mukherjee 1994, hlm. 454–6.
- ^ MacQueen 2005, hlm. 314–5.
- ^ Mukherjee 1994, hlm. 457.
- ^ Gombrich 2018, hlm. 73.
- ^ Findly 2003, hlm. 376–7.
- ^ Kinnard, Jacob (2006). "Buddhism" (PDF). Dalam Riggs, Thomas. Worldmark Encyclopedia of Religious Practices. Thomson Gale. hlm. 62. ISBN 0-7876-6612-2. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 11 September 2018.
- ^ a b Satu atau lebih kalimat sebelum ini menyertakan teks dari suatu terbitan yang sekarang berada pada ranah publik: Rhys Davids, Thomas William (1911). "Ānanda". Dalam Chisholm, Hugh. Encyclopædia Britannica. 1 (edisi ke-11). Cambridge University Press. hlm. 913.
- ^ Mun-keat, Choong (2000). The Fundamental Teachings of Early Buddhism: A Comparative Study Based on the Sūtrāṅga Portion of the Pāli Saṃyutta-Nikāya and the Chinese Saṃyuktāgama (PDF). Harrassowitz. hlm. 142. ISBN 3-447-04232-X. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 October 2012.
- ^ Findly 2003, hlm. 395.
- ^ Hansen 2008, hlm. 51.
- ^ Findly 2003, hlm. 378.
- ^ Pāsādika, Bhikkhu (2004). "Ānanda" (PDF). Dalam Buswell, Robert E. Encyclopedia of Buddhism. 1. Macmillan Reference USA, Thomson Gale. hlm. 17. ISBN 0-02-865719-5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 September 2015.
- ^ Findly 2003, hlm. 370.
- ^ Buswell & Lopez 2013.
- ^ Clasquin 2013, hlm. 7.
- ^ Gethin 2001, hlm. 232.
- ^ Gethin 2001, hlm. 232–4.
- ^ a b Findly 2003, hlm. 375–6.
- ^ Findly 2003, hlm. 372, 390–1.
- ^ a b Shaw 2006, hlm. 115.
- ^ Swearer, Donald K. (1995). The Buddhist World of Southeast Asia. SUNY Press. hlm. 209. ISBN 978-0-7914-2459-9.
- ^ Findly 2003, hlm. 379.
- ^ Filigenzi 2006, hlm. 270–1.
- ^ Findly 1992, hlm. 261–3.
- ^ Findly 2003, hlm. 378–9.
- ^ Bareau, André (1991). "Les agissements de Devadatta selon les chapitres relatifs au schisme dans les divers Vinayapitaka". Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient (dalam bahasa Prancis). 78 (1): 92, 94–5, 107, 109–10. doi:10.3406/befeo.1991.1769.
- ^ Findly 2003, hlm. 373.
- ^ a b c Baruah 2000, hlm. 10.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Madhyāntika.
- ^ Baruah 2000, hlm. 8.
- ^ a b c Strong 1994, hlm. 65.
- ^ Baruah 2000, hlm. 8, 453.
- ^ Witanachchi 1965, hlm. 534–5.
- ^ John S. Strong (2007). Relics of the Buddha. hlm. 45–46. ISBN 978-0691117645.
- ^ Ray 1994, hlm. 109.
- ^ Vogel, Jean-Philippe (1905). "Le Parinirvàna d' nanda, d'après un bas-relief gréco-bouddhique" [Ānanda's Parinirvāna, According to a Greco-Buddhist Bas-relief]. Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient (dalam bahasa Prancis). 5 (1): 418. doi:10.3406/befeo.1905.2660.
- ^ Strong 1994, hlm. 66.
- ^ Higham, Charles F. W. (2004). Encyclopedia of Ancient Asian Civilizations (PDF). Facts On File. hlm. 10. ISBN 0-8160-4640-9.
- ^ Cousins, L. S. (2005). "The 'Five Points' and the Origins of the Buddhist Schools" (PDF). Dalam Skorupski, T. The Buddhist Forum Volume II: Seminar Papers 1988–90. Routledge. hlm. 30. ISBN 978-1-135-75237-8. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 September 2018.
- ^ Keown, Michelle (2004-12-17). Postcolonial Pacific Writing. Routledge. ISBN 978-0-203-50679-0.
- ^ Open boundaries : Jain communities and culture in Indian history. John E. Cort. Albany, NY: State University of New York Press. 1998. ISBN 0-585-06970-0. OCLC 44959977.
- ^ a b c d e f g h Creel, Austin B. (1975-04). "The Reexamination of "Dharma" in Hindu Ethics". Philosophy East and West. 25 (2): 161. doi:10.2307/1397937. ISSN 0031-8221.
- ^ Day, L.E. (1982). SYSTEMS ENGINEERING CHALLENGES OF THE SPACE SHUTTLE. Elsevier. hlm. 23–42.
- ^ a b Strong, John (1994). The legend and cult of Upagupta : Sanskrit Buddhism in north India and Southeast Asia (edisi ke-1st Indian ed). Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. ISBN 81-208-1154-2. OCLC 32319630.
- ^ a b c d Buswell, Robert E.; Lopez, Donald S. (2014-01-01). The Princeton Dictionary of Buddhism. Princeton University Press. ISBN 978-1-4008-4805-8.
- ^ Toney, Michael F. (1994). Studies of Electrodes by in Situ X-Ray Scattering. Dordrecht: Springer Netherlands. hlm. 109–125. ISBN 978-90-481-4406-8.
- ^ Yakan. Cham: Springer International Publishing. 2016. hlm. 361–361.
- ^ a b Baruah, Nayandeep Deka (2000). "A Few Theta-Function Identities and Some of Ramanujan's Modular Equations". The Ramanujan Journal. 4 (3): 239–250. doi:10.1023/a:1009835301693. ISSN 1382-4090.
- ^ a b Buddhism : critical concepts in religious studies. Paul Williams. London: Routledge. 2005. ISBN 0-415-33226-5. OCLC 57493685. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-07. Diakses tanggal 2022-08-11.
- ^ a b Paultre de Lamotte, Jacques (1988). "Fiscalité des O.P.C.V.M". Revue française d'économie. 3 (1): 81–95. doi:10.3406/rfeco.1988.1169. ISSN 0769-0479.
- ^ Holy people of the world : a cross-cultural encyclopedia. Phyllis G. Jestice. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO. 2004. ISBN 1-85109-649-3. OCLC 57407318.
- ^ Higham, Charles (2004). Encyclopedia of ancient Asian civilizations. New York: Facts On File. ISBN 0-8160-4640-9. OCLC 51978070. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-07-15. Diakses tanggal 2022-08-11.
- ^ Collected papers on Buddhist studies. Padmanabh S. Jaini (edisi ke-1st ed). Delhi: Motilal Banarsidass Publishers. 2001. ISBN 81-208-1776-1. OCLC 47208728.
- ^ a b The Venerable Balangoda Ānanda Maitreya:. Princeton University Press. 2021-03-09. hlm. 299–313.
- ^ Findly 2003, hlm. 381.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Atthakanāgarasutta; Bhaddekarattasutta.
- ^ Norman 1983, hlm. 48.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Sekhasutta; Subhasuttanta.
- ^ Clasquin 2013, hlm. 10.
- ^ a b c Wijayaratna 1990, hlm. 153.
- ^ Clasquin 2013, hlm. 10–11.
- ^ Reynolds, Frank; Shirkey, Jeff (2006). Safra, Jacob E.; Aguilar-Cauz, Jorge, ed. Britannica Encyclopedia of World Religions. Encyclopaedia Britannica. hlm. 47. ISBN 978-1-59339-491-2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-10-02. Diakses tanggal 2019-09-17.
- ^ Nishijima, Gudo Wafu; Cross, Shodo (2008). Shōbōgenzō : The True Dharma-Eye Treasury (PDF). Numata Center for Buddhist Translation and Research. hlm. 32 n.119. ISBN 978-1-886439-38-2. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2 August 2017.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Damoduoluo chan jing; Madhyāntika.
- ^ Welter, Albert (2004). "Lineage" (PDF). Dalam Buswell, Robert E. Encyclopedia of Buddhism. 2. Macmillan Reference USA, Thomson Gale. hlm. 462–3. ISBN 0-02-865720-9. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-06-29. Diakses tanggal 2019-09-16.
- ^ Baruah 2000, hlm. 9, 453.
- ^ Strong 1994, hlm. 62.
- ^ Hirakawa 1993, hlm. 86.
- ^ Buswell & Lopez 2013, Er xieshi.
- ^ Edkins, Joseph (2013). Chinese Buddhism: A Volume of Sketches, Historical, Descriptive and Critical. Routledge. hlm. 42–3. ISBN 978-1-136-37881-2.
- ^ Lamotte 1988, hlm. 210.
- ^ Gyatso, Janet (2014). "Female Ordination in Buddhism: Looking into a Crystal Ball, Making a Future". Dalam Mohr, Thea; Tsedroen, Jampa. Dignity and Discipline: Reviving Full Ordination for Buddhist Nuns. Simon and Schuster. ISBN 978-0-86171-830-6.
- ^ Ambros 2016, hlm. 210–12, 214, 216–8, 245–6.
- ^ Wijayaratna 1990, hlm. 36.
- ^ Gombrich, Richard (1995). Buddhist Precept and Practice: Traditional Buddhism in the Rural Highlands of Ceylon. Routledge. hlm. 240. ISBN 978-0-7103-0444-5.
- ^ a b Gutman, Pamela; Hudson, Bob (2012). "A First-Century Stele from Sriksetra". Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient. 99 (1): 29. doi:10.3406/befeo.2012.6151.
- ^ a b Svasti, Pichaya (4 May 2017). "The Path to Nirvana". Bangkok Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 October 2018. Diakses tanggal 24 September 2018.
- ^ a b Wagner, R. (10 August 1889) [1856]. "Sketch of Wagner's 'Die Sieger'". The Musical World. 69 (32): 531. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 October 2018.
- ^ "Jonathan Harvey's Wagner Dream, Opera on 3 - BBC Radio 3". BBC. May 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 November 2015.
- ^ App 2011, hlm. 42–3.
- ^ App 2011, hlm. 33–4, 43.
- ^ App 2011, hlm. 34–5:"... und somit seine erlösenden, allen Wesen zugewendeten Weltlauf als volendet ansieht, da er auch dem Weibe—unmittelbar—die Erlösung zusprechen konnte."
- ^ Jain, R. (2016). "Tagore's Drama Synthesis of Myths, Legends and Folklores: A Medium of Social Reformation". Dialogue – A Journal Devoted to Literary Appreciation. 12 (1): 71. ISSN 0974-5556. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 October 2018. Diakses tanggal 1 October 2018.
- ^ Chowdurie, Tapati (27 April 2017). "Quenching Prakriti's Thirst..." The Hindu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 October 2018. Diakses tanggal 24 September 2018.
Pranala luar
sunting- Ānanda: Penjaga Dhamma, oleh: Hellmuth Hecker; alih bahasa: Lestoro, diterbitkan oleh: Yayasan Sayap Prabha - Jl. Hanura II no. 19, Jakarta Barat. Jaringan Informasi Buddhis Samaggi-Phala
- Kannakatthala Sutta, Pusat Meditasi Vipassana Graha Diarsipkan 10 Mei 2011 di Wayback Machine.